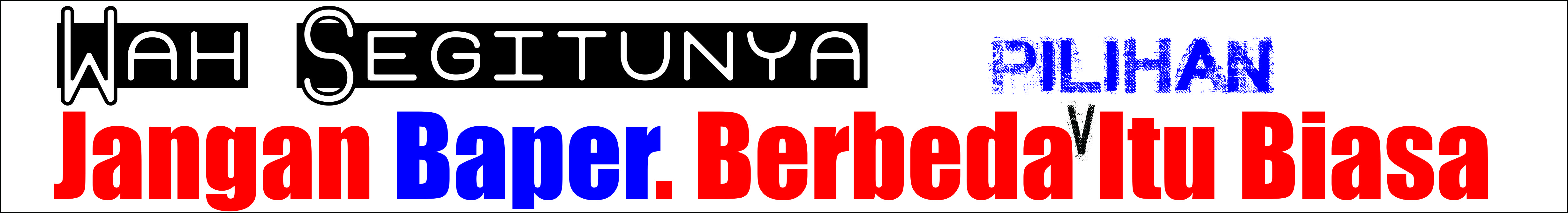Musim hujan kembali lagi. Langit berwarna abu-abu tua. Saya melamar kerja sebagai wartawan di majalah Momentum Nusantara. Kantor majalah ini terletak di daerah Tebet, Jakarta, di sebuah rumah berlantai dua, bergaya modern. Dua minggu kemudian, lamaran saya diterima.
Pada akhir November, Momentum Nusantara sudah tak ada. Majalah itu berganti bentuk menjadi tabloid bernama Lestari, tanpa alasan yang saya ketahui.
Seorang pria menemui saya di ruangan berpartisi biru muda itu. Ia mengenakan kemeja katun bermotif kotak-kotak kuning, hijau, dan oranye dari bahan sederhana. Begitu pula pantalon coklat mudanya. Lingkaran hitam di bawah sepasang mata yang letih mulai samar-samar, tidak seperti pertama kali kami bertemu. Ia berkulit agak gelap dengan bobot yang tidak bisa disebut langsing.
Andy Suwarto adalah editor Lestari. Ruangannya berisi dua meja tulis. Satu meja Andy dan satu lagi meja sekretaris. Seorang perempuan yang datang lebih dulu memperkenalkan diri. Ia sama-sama melamar kerja dan mengaku pernah jadi wartawan di majalah Konstruksi, majalah arsitektur. Kami duduk berdampingan di muka meja Andy. Dinding ruangan berwarna krem. Udara AC terasa sejuk.
“Saya sudah membuat proposalnya dan Linda ditempatkan meliput rubrik pariwisata serta seni dan budaya. Nama media kita tidak jadi Momentum Nusantara, tapi Lestari. Bentuknya tabloid,” kata Andy.
“Terbit mingguan atau dua mingguan?”
“Rencana saya, dalam bulan Desember terbit dua kali. Bulan Januari terbit tiga kali. Bulan Juni terbit enam kali.”
“Saya tidak tahu seperti apa tulisan yang diinginkan Lestari,” tukas saya.
Ia sibuk membuka tas, tapi menutupnya lagi.
“Sekedar contoh saja. Kira-kira bentuk tulisannya seperti apa,” desak saya.
Andy lalu mengeluarkan tabloid Selaras dari dalam tasnya. Sosok model sampul mulai terlihat. Wajah seorang penyanyi terkenal. Yuni Shara tengah berendam di laut hanya mengenakan kutang dan kain batik.
Ia membuka-buka halaman Selaras, lantas menunjuk sebuah artikel. Andy minta saya membuat tulisan macam itu. Artikel tersebut berada pada halaman 14 dalam rubrik “Serba-Serbi”. Judulnya, “Film Layar Lebar Joshua.”
“Lestari satu grup dengan Selaras ini?”
“Oh, nggak. Kita satu grup dengan Momentum Nusantara,” jelas Andy.
Dalam masthead Selaras tercantum nama ‘Andy Suwarto’. Posisinya, wartawan.
“Begini saja. Untuk rubrik pariwisata itu misalnya, di Cirebon kan terkenal dengan ikan pepesnya, yang tulangnya bisa dimakan, karena lunak sekali. Kita lihat bagaimana mereka mengolahnya. Itu bisa jadi tulisan untuk pariwisata. Atau di Banten yang terkenal dengan ikan tanpa tulang. Hebat kan?” katanya.
“Boleh juga.”
“Menarik, lho mengamati bagaimana para nelayan membawa ikan dan istri mereka menarik tulang-tulang ikan itu di malam hari. Kamu harus menunggu sampai malam dan melihat mereka melakukannya,” kata Andy, lagi.
“Menarik. Meliput sambil rekreasi,” tukas saya.
“Nah, kalau tulisan itu sudah jadi dan dimuat, mungkin Surya Paloh, Arifin Panigoro, dan pengusaha-pengusaha itu akan melihat bahwa daerah tersebut berpotensi besar untuk usaha mereka. Kita lalu buat proposalnya. Berapa biaya untuk pembibitan ikan, pengolahan ikan, dan sebagainya. Setelah itu kita ajukan kepada mereka, sehingga proyek tersebut kita yang ngurus. Kita dapat uang dari sana.”
Ia terus berbicara.
“Atau Anda kan di seni dan budaya, ya? Anda liput pameran lukisan, misalnya. Wawancarai pelukisnya, tanyakan mengapa ia memilih profesi pelukis, bukankah banyak profesi lain yang lebih baik untuk mencari nafkah. Kita muat tentang pelukis ini, kemudian kita potret lukisannya. Sehingga ketika ada orang yang membaca dan tertarik membeli lukisan itu, ia akan menghubungi Linda yang membuat tulisan itu. Saya ingin beli lukisan si ini, katanya. Linda tinggal bilang, sebentar saya hubungi pelukisnya. Linda kan tahu nomor telepon pelukisnya. Kita jadi mediator untuk penjualan lukisan. Kalau harga lukisan dua juta, kita bisa dapat 500 ribu. Kan lumayan. Istilahnya, masak sih ia nggak mau membelikan semangkuk bakso buat kita?” ujarnya, seraya tertawa.
“Asyik juga, ya?”
“Iya. Saya dulu kan begitu, Linda,” sahut Andy.
Pria ini bercerita bahwa ia pernah mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 107 di Pasar Minggu, Jakarta. Ketika saya menanyakan alasannya berubah profesi menjadi wartawan, ia tertawa kecil. “Nah, kalau soal itu tanyakan pada istri saya,” katanya, seraya tersenyum.
Andy mengusulkan tiga topik berita. Pertama, mempertanyakan keabsahan data statistik sektor wisata di Indonesia yang disebutkan sudah mencapai target. Padahal, masih ada daerah wisata yang belum tersentuh. Saya diminta mewawancarai Menteri Pariwisata I Gde Artana dengan mengirim faksimili lebih dulu kepada petugas hubungan masyarakatnya, Adelia Raung. Bila tidak berhasil mewawancarai menteri, Direktur Jenderal Pariwisata Jusmiati Anwar target selanjutnya. “Terus kamu kembangkan, deh,” kata Andy.
Kedua, membuat tulisan tentang Kafe Galangan di Kota, dekat Pasar Ikan. “Di sana ada kafe, diskotik …. Biasanya beroperasi di malam hari. Mungkin, kamu harus meliput malam hari,” tegasnya. Ketiga, mewawancarai pengusaha. “Linda kenal pengusaha nggak?” tanya Andy. Saya mengatakan ‘tidak’. Perempuan dari majalah Konstruksi mengusulkan Daniel Hutapea, ketua Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia cabang Jakarta untuk diwawancarai.
Tiba-tiba terlintas di benak saya menanyakan fasilitas peliputan, gaji, tunjangan, dan kontrak kerja pada Andy. Sejak kemarin ia tidak menyinggungnya. Andy Suwarto gelagapan ketika menjawab soal gaji. “Enaknya bagaimana? Per bulan atau per tulisan?” Ia malah bingung. Akhirnya, disepakati saya akan digaji setiap bulan dengan syarat minimal menyetor dua tulisan setiap hari.
Di luar ruangan Andy, Surtiadi, sesama wartawan Lestari yang juga bekerja sebagai fotografer tabloid Delta, datang menjelang pukul 09.30. Ia bercerita gajinya di Delta Rp 500 ribu setiap bulan, tanpa uang makan, uang transport, dan penggantian biaya peliputan. “Untung saya ada tambahan dari luar. Kalau nggak, nggak cukup,” katanya.
Surtiadi lantas bertutur ia dulu sering meliput bersama tiga wartawan lain, dua di antaranya wartawan tabloid Profile yang sudah almarhum. Profile tabloid hiburan yang memamerkan kesintalan tubuh perempuan. Judul-judul artikelnya berani, semacam “Menelusuri Jejak Bisnis Lendir”. Trik-trik mencapai kepuasan berhubungan seksual dipaparkan rinci di situ.
Melalui Surtiadi, saya jadi tahu cara mereka memperoleh model-model seksi.“Cewek-cewek itu yang membayar. Untuk tampil di cover Rp 3 juta. Uangnya bisa masuk kantong kita. Model-model daerah mau membayar mahal. Delta tersebar di 15 propinsi,” ujar Surtiadi, berpromosi.
Ia menganjurkan saya pergi ke Taman Mini Indonesia Indah untuk mencari materi liputan seni dan budaya. Brosur-brosur wisata dari berbagai daerah bisa diperoleh di sana. “Lagipula, di sana ada jatahnya, lho. Lumayan,” tukas Surtiadi, meyakinkan.
Jatah, kata lain untuk menyebut amplop.
sELAMA menjalani pekerjaan ini sejak 1999 saya jadi banyak berpikir. Melarang wartawan menerima amplop tidak sama dengan melarang orang melahap jajanan penuh sambal atau makan bersama lalat di pinggir jalan, yang bisa membahayakan pencernaannya sendiri. Menghilangkan kebiasaan tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Ada pihak industri media yang mampu menggaji layak. Ada juga faktor pendidikan wartawan yang memadai. Ada serikat buruh yang berani membela kepentingan wartawan dalam berhadapan dengan manajemen suratkabar, radio atau televisi. Wartawan hanya simpul kecil dari gurita industri media.
Nezar Patria dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang bekerja pada Tempo Interaktif, mengatakan sebenarnya semangat jurnalistik yang tercermin dari sikap menolak amplop itulah yang terpenting. “Intinya menolak amplop untuk menegakkan sikap jurnalistik independen. Bisa saja kita berganti-ganti media, tapi karya jurnalistik ini dipandang sebagai karya individu. Sifatnya pribadi. Dalam proses jurnalistik melakukan pelanggaran kode etik, individu yang dituntut,” Nezar menerangkan alasannya. Sikap menolak amplop berlandaskan kebebasan alias independensi, bukan penindasan atau keterpaksaan. Bebas dari hal-hal yang membuat orang tak punya pilihan.
Dalam sebuah penelitiannya, wartawan EH Kartanegara mengungkapkan 76 (92,68%) orang wartawan menerima amplop dari 82 wartawan yang ditelitinya di berbagai kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan Kartanegara pada 1989 untuk kolom di harian Kompas. Kartanegara mengatakan “amplop” adalah “obat mujarab” buat wartawan.
Bersama seorang teman, saya memutuskan datang ke sebuah hotel di jalan KS Tubun, Jakarta, untuk mengetahui aktivitas wartawan amplop di sana. Di sanapetugas keamanan partai berlambang kepala banteng itu berseragam hitam-hitam, berjaga-jaga di muka hotel. Pembukaan rapat nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimulai pukul 19.00. Di lantai dua seorang wanita melayani para wartawan, mencatat dan memberi tanda pengenal. Saya memberi kartu nama. Tapi, ia menolak memberi kartu pengenal. “Saya tidak pernah melihat Anda di lapangan,” tukasnya, ketus. Dua orang wartawan yang mengaku dari tabloid Komunitas berada di dekat kami. Seorang di antara mereka mengulangi pertanyaan yang sama, “Dari media mana?” Setelah berkali-kali meminta kartu pengenal, wanita itu luluh juga. Hanya satu kartu pengenal untuk dua orang.
Permadani merah terhampar menuju pintu masuk ruang rapat. Para penjaga berseragam batik memeriksa tanda pengenal peserta. Seorang pria membuka laci-laci tas saya. Gel pembasuh muka Biore tersembul dari kantung paling bawah. Saya mulai gugup. Mungkin, sebentar lagi celana dalam dan pembalut melompat dari dalam tas. Ia menoleh dan berkata, “Seharusnya cewek yang memeriksanya.” Ia menghentikan pemeriksaan dan menyerahkan tas itu kembali.
Meja-meja panjang berisi makan malam tersaji. Dua orang wartawan Komunitas membuntuti. Wartawan yang tadi menegur di meja pendaftaran mendekat, lalu berceloteh tentang tugas meliput seni dan budaya. Temannya sibuk mondar-mandir. Wanita bagian pendaftaran muncul dan bergabung. Rupanya wartawan Komunitas dan wanita itu saling mengenal. Si wanita wartawati tabloid Progresif. Mereka berbincang-bincang seputar amplop di gedung parlemen. Mereka biasa mangkal di sana.
“Waktu itu saya dikasih 100 ribu. Kami berempat. Eh, masak bapak itu menyuruh saya menukar uang itu untuk dibagi empat. Yang benar saja, 100 ribu dibagi empat,” tutur wartawan Komunitas. Tawa mereka berderai.
Seorang pria yang sejak tadi duduk bersila di dekat kami tiba-tiba bertanya, “Adik berdua dari mana?” Katanya, ia baru menjadi wartawan dan tidak mempunyai latar belakang jurnalistik. Nama pria ini Abdullah, dari tabloid Metropolitan.
“Saya tidak mempunyai latar belakang jurnalistik, baru bergabung. Pemimpin redaksinya, Pak Bastian itu lulusan dari luar negeri, dari Jerman. Kalau adik mau, adik bisa belajar dan bertanya banyak dari dia. Ini nomor handphone-nya. Bisa ngomong langsung. Silahkan. Coba aja ngobrol-ngobrol,” ujar Abdullah setengah memaksa. Ia sudah menekan angka-angka pada telepon genggamnya. Nomor telepon genggam sang pemimpin redaksi. Abdullah suka rela memberikan nomor ini. Ia berharap banyak pada kami. Menurutnya Metropolitan membutuhkan banyak wartawan. Metropolitan terbit dua mingguan. Setelah mencatat alamat dan nomor telepon Metropolitan, kami masuk ke ruang pertemuan.
Pidato-pidato segera dimulai. Roy BB Janis, salah seorang tokoh PDIP, memberi sambutan. Wajah-wajah dari media tak dikenal menduduki mayoritas kursi wartawan. Ada yang membawa kamera kecil. Saya teringat informasi seorang teman, “Wartawan bodrex biasanya membawa kamera pocket.”
“Wartawan bodrex,” istilah sesama wartawan untuk menjuluki mereka yang mengejar uang dengan kedok mencari berita.
Di belakang kursi kami, juru kamera salah satu stasiun televisi berdiri. Amplop untuk wartawan televisi lebih besar ketimbang media cetak. Jumlahnya bisa 500 ribu sampai satu juta. Seorang anggota parlemen malah berterus-terang mempunyai “peliharaan” berupa wartawan-wartawan di dua stasiun televisi. Bahkan, menurut dia, banyak politisi di parlemen “memelihara” wartawan dan memberi mereka sumbangan uang secara rutin.
Bau ketiak seorang wartawan yang duduk di sebelah saya menusuk hidung. Ia mengenakan kemeja batik, menggenggam kamera saku, dan menatap nyalang. Rahangnya persegi. Tipikal wajah semacam ini banyak terlihat dalam ruang tersebut.
PRIA Tapanuli yang berbicara blak-blakan dan cepat itu menerima saya di ruang kerjanya. Saya duduk di kursi tamu berlapis kulit warna coklat dan mengamati seisi ruangan. Jam dinding menunjukkan pukul 09.00. Dua buah piagam penghargaan terletak di atas meja kerjanya. Potret berpigura yang terpasang di dinding memperlihatkan ia tengah bersama Adnan Buyung Nasution, pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Monang Saragih mendirikan Radio Mora pada 1999, setelah proses perizinan yang panjang sejak 1984. “Pada masa Orde Baru pendirian media tidak semudah sekarang,” tuturnya, sambil tersenyum. Saragih berprofesi sebagai pengacara sekaligus pemilik sebuah radio yang terkenal dengan rubrik hukumnya di Bandung. Radio Mora berkantor di Jalan Peta Selatan, di pinggir jalan raya yang sibuk.
Ia menganggap pelarangan wartawan menerima amplop atau imbalan dari narasumber tidak memiliki dasar hukum. Orang yang tidak tahu hukum membuat peraturan yang aneh-aneh. Sok bikin peraturan. AJI kejam. Bahkan, industri persnya juga lebih kejam.
“Saya tidak melarang. Contohnya reporter kami di sini. Saya katakan, kalau ada pihak-pihak yang memberikan uang terima saja. Banyak perusahaan sangat melarang itu, mengharamkan. Jadi saya katakan pada mereka pemberian orang lain itu silahkan diterima. Bahkan, saya bilang di dalam menjalankan profesi ini kita kalau bisa multi penghasilan. Mereka ini kan sudah dapat dari medianya, dapat lagi dari saya satu berita Rp 10 ribu, dan dapat lagi pemberian dari narasumber. Saya bilang, terima saja. Tapi, pemberitaan jangan terganggu.”
Bagaimana memastikan bahwa amplop itu tidak berpengaruh terhadap berita?
Menurut Saragih, itu perkara mudah. Ketika isi berita tersebut tidak sesuai dengan penugasan sudah pasti harus dicurigai. Radio Mora mempunyai sekitar 30 orang reporter. Mereka berasal dari media cetak maupun elektronik. Saragih tidak melarang wartawannya bekerja rangkap. Baginya yang penting jam kerja yang telah ditetapkan dipenuhi. “Hari kan ada 24 jam. 24 jam itu kan bisa dipakai 12 jam kerja sehari, sebagai orang susahlah gitu, ya. Sebagai orang makmur bolehlah kalau 8 jam kerja. Masak habis untuk satu media saja. Kalau saya bekerja 12 jam sehari 16 halaman koran itu sudah penuh oleh saya sendiri. Ini wartawan 12 jam dalam satu media,” ujarnya, bersemangat.
Namun, pria ini tidak setuju dengan tindakan pemerasan terhadap narasumber. “Oh, itu jelas kejahatan. Ada deliknya. Kalau tadi penyuapan. Narasumber menyuap agar beritanya jangan dimuat dan versi dia yang dimuat, itu satu penyuapan. Nah, sekarang itu pemerasan. Ada juga orang tahu sedikit informasi, entah berita burung apa, langsung dia konfirmasi ke sana, minta wawancara, kemudian orang itu kalau tidak memberi imbalan, maka berita negatif itu akan dibeberkan. Sama-sama jahat. Memeras jahat. Menyuap jahat.”
Pemerasan ini bisa dituntut?
“Bisa. Dua-duanya kena itu. Kalau pemerasan jelas yang memerasnya ini kena. Tapi, saya pikir, kalau pejabat yang diperas dan dia memberi itu, dia juga minimal membantu pemerasan.”
Saragih lantas bercerita bahwa di Bandung ada sekelompok wartawan yang tidak memiliki media. Mereka sering berkumpul di sebuah gedung yang terletak di Alun-Alun.
“Di sana itu ada yang namanya wartawan Mandala. Mandala kan sudah lama nggak terbit. Wartawannya nggak bubar. Kartu persnya berlaku terus dan mereka anggota Persatuan Wartawan Indonesia. Inilah yang memeras umumnya. Atau kalau pun ada tabloid yang terbit, itu semaunya mereka. Ya, ada uang terbit. Nggak ada uang, nggak terbit Itulah pemeras itu.”
Saya ingin tahu pendapatnya dan tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi masalah ini.
“Tindakan yang harus dilakukan adalah PWI sebagai induk organisasi ini harus mengambil orang ini, jangan dibiarkan saja. Karena mereka butuh hidup. Dia punya keahlian, punya kemampuan investigasi, dia tahu informasi, saluran beritanya yang nggak ada. Jadi, terpaksa meras kan? Kadang-kadang lucunya, hasil dari pemerasan itu, berita itu mereka berikan ke kawannya yang ada di Pikiran Rakyat, di koran yang bagus, honornya mereka bagi dua.”
Saragih juga menyalahkan peraturan dalam industri pers yang kaku, melarang wartawan bekerja rangkap. “Sudah rendah penghasilannya, dibikin peraturan yang macam-macam. Akhirnya, mereka kan jadi pencuri. Banyak rumah tangga bercerai, gara-gara nggak boleh kerja rangkap, sedang gaji kecil. Akhirnya nyeleweng dari tugas pers, ” tukasnya.
Tidakkah sebaiknya media tempat wartawan itu bekerja yang harus memenuhi kebutuhan wartawan agar mereka tidak memeras orang? Saragih justru melihatnya dari sisi yang berbeda. “Kalau mampu,” ucapnya, membela. Ia menganggap organisasi atau serikat wartawan belum mampu memperjuangkan kesejahteraan dan nasib wartawan. “Mereka masih sibuk berpolitik. Jadi, mereka membuat organisasi ini dalam rangka kepentingan politik saya lihat, seolah-olah menampung aspirasi anggotanya dan memperjuangkan kepada penguasa. Itu salah satu, bolehlah. Tapi, jangan melulu itu. Kesejahteraan ini nggak disentuh, sama sekali.”
Berapa persentase wartawan yang memaksa narasumber memberi amplop di Bandung?
“Yang memaksa sebenarnya mereka itu tidak terlalu banyak. Cuma mereka militan. Sedikit tapi menonjol. Kenapa mereka menonjol? Karena mereka militan dan penghasilannya tinggi dari cara begitu. Bisa dapat seratus juta mereka dari satu persoalan. Wartawan yang menerima amplop ini paling seratus ribu. Itu kan saya tahu.”
Gaji wartawan suratkabar Bandung Pos dan Sinar Pagi di Bandung Rp 150 ribu. Gala Media tidak jauh berbeda. “Suka telat lagi. Gaji wartawan ini di bawah upah minimal buruh. Buruh saja minimal sudah Rp 375 ribu. Wartawan Anteve juga sulit. Di RCTI harus punya kamera sendiri dan setelah beritanya dimuat baru dibayar, sekitar Rp 1 juta sampai Rp1,5 juta,” keluh Saragih.
AJI melarang tegas wartawan menerima amplop. Sofyan Lubis dari PWI berpendapat amplop boleh diterima asal tidak mempengaruhi pemberitaan.
“Menerima amplop itu sama dengan pelacuran,” kata Budiman S. Hartoyo dari PWI Reformasi. Ia menganggap para kapitalis media yang bergabung dalam Serikat Penerbit Suratkabar justru paling bertanggung jawab terhadap berkembangnya kebiasaan wartawan menerima amplop.
TAKSI meluncur ke muka pintu utama sebuah hotel berbintang lima di kawasan Semanggi. Pelayan hotel membukakan pintu taksi. Pukul 20.30. Kursi-kursi di lobi sebagian besar terisi. Udara dingin mengelus pori-pori. Gemuruh air mancur di tengah ruangan menyamarkan suara percakapan. Saya datang terlampau cepat. Pria itu bersedia ditemui pukul 21.00. Ia tengah mengikuti pertemuan radio yang diselenggarakan Unesco Jakarta. Saya duduk di salah satu kursi, menunggu, dan mengeluarkan novel Milan Kundera dari Czech. Seorang pria Jepang yang galant duduk di hadapan saya. Ia bertanya dalam bahasa Inggris. Apakah boleh merokok? Saya mengangguk setuju dan kembali merenungi halaman-halaman novel L’immortalite tadi. Sesekali mengintipi eskalator. Siapa tahu ada yang dikenal.
Pukul 21.00 saya meminta resepsionis menghubungi kamar 1431 atau 1403. Kedua-duanya kosong. Setelah menanggung rasa kesal dan bolak-balik mengganggu resepsionis itu, saya disuruh ke lantai M. Di sanalah ruang pertemuan tersebut.
Di lorong menuju ruang pertemuan, terdengar suara seorang pria berbicara dalam bahasa Inggris diikuti suara penerjemahnya. Pria setengah baya di samping pintu masuk menawarkan jasa untuk menghubungi orang yang saya cari dan memberitahu kehadiran saya.
Entah berapa lama terlihat mencolok mata para peserta. Acara itu memang tidak untuk diliput. Tentu saja kehadiran wartawan mengundang pertanyaan mereka.
Pelayan-pelayan hotel berkemeja putih dan pantalon hitam lalu-lalang. Pria itu datang juga. Ia meminta saya menunggu lagi. Acara farewell party tengah berlangsung. Peserta saling tukar-menukar cendera mata. Seorang pelayan membantu menggotong sebuah lukisan wayang. Tokohnya, Srikandi. Dari dalam ruangan terdengar orang saling bersulang. Pidato-pidato singkat yang akrab silih-berganti. Denting piano mengalun dan arus lamban manusia ke luar ruangan.
Semula saya berencana mewawancarai Jojo Prasetyo dari radio Kaltara di kamarnya. Tapi, batal. Teman-teman sekamar Jojo berbicara keras-keras. Suara mereka bisa terekam. Akhirnya, kami pun bercakap-cakap di kafe hotel. Gadis-gadis cantik mengenakan gaun pendek berlengan spaghetti ataupun model bustier tampak berkeliaran di lobby. “Barangkali, ada pesta,” ujar Jojo, menggerutui kecantikan para gadis yang menggoda. Pelayan menyodorkan menu.
Sepasang matanya agak sipit. Ia tertawa saat saya menyampaikan jawaban resepsionis yang memastikan tidak ada penghuni kamar 1431 yang bernama ‘Jojo Prasetyo’. “Jojo itu nama panggilan saya. Waktu kecil saya dipanggil Bejo.” Jojo menatap lurus.
Ia tidak setuju wartawan menekan narasumber untuk memperoleh amplop. Lebih baik jadi tukang pukul saja, sindirnya. Namun, ia tidak sependapat dengan AJI yang melarang keras wartawan menerima amplop tanpa memandang bulu. Amplop yang disediakan panitia pertemuan-pertemuan pers itu bernilai promosi. Dananya sudah dianggarkan. Tak berpengaruh terhadap masyarakat. “Kalau diberi terus nggak mau, kayak AJI tadi ekstrem sekali, ya? Kalau toh Anda belum tahu kasus saya apa, kemudian saya bilang, ‘Lin, ini ada uang saku untuk kamu.’ Kamu tolak mentah-mentah. Kaya amat kamu! Naik Baby Benz nggak?”
Pelayan bergaun hitam ketat itu kembali menawarkan minuman.
Pria ini memberi kiat dalam menolak amplop.
“Kalau diberikan amplop dan kita masih mempunyai tanggungan berita terhadap narasumber, toh, alangkah baiknya ditolak untuk sementara, karena itu akan mempengaruhi isi berita. Dalam mencari berita jangan sampai kita tersentuh oleh kepentingan finansial. Kalau liputan Anda sudah selesai, Anda meminta lebih baik. Lebih baik meminta. Kita juga bisa ngetes orang. Setelah dia kita beritakan begini-begini, dia masih bisa baik nggak. Apa salahnya, sih kita meminta bantuan pada seseorang, sementara kita kekurangan? Nggak salah kan orang meminta, karena penghasilan yang kurang?” tuturnya, serius. Gaji pokok wartawan di radionya Rp 200 ribu.
Sekali meminta ia pernah diberi Rp 500 ribu. Jojo berterus-terang dekat dengan walikota Tarakan, Kalimantan. Apakah ia pernah disogok narasumber? Katanya, ia malah diteror. Suatu hari ada orang menelepon, bahkan ada orang suruhan yang mengantar sejumlah uang. Pengirimnya tak dikenal. Ia malah takut. Selidik punya selidik, ternyata uang itu berasal dari pengusaha yang terlibat pencurian kayu. Radio Kaltara menyiarkan kasus ini. Jojo tidak bersedia memberikan angka nominal uang sogokan tadi. “Yang jelas satu amplop airmail penuh,” ujarnya. Sogokan tidak hanya berupa uang, juga perempuan.
Jojo tidak menjadi anggota organisasi atau serikat wartawan. Alasannya, birokrasi AJI berbelit-belit, sedang PWI sudah dikotori perbuatan anggotanya yang suka memeras.
Pukul satu dini hari. Suara gemuruh air mancur tak terdengar lagi. Kafe sudah sepi. Tapi, gadis-gadis cantik masih duduk-duduk di lobi. Mereka bercengkrama tak kenal waktu. Saya memutuskan meninggalkan hotel menjelang subuh. Tak ada orang yang bersedia membuka gerbang di malam buta. Jojo mengajak saya ke kamarnya. Kami naik lift ke lantai 14. Kamar-kamar berderet di sepanjang lorong dengan penerangan yang redup. Seorang pelayan hotel tengah mencatat sesuatu dalam bukunya, duduk di kursi sambil mengawasi. Kami mengucapkan selamat malam. Jojo mengeluarkan kartu, membuka pintu. Udara dingin AC menerpa sekujur tubuh saya. Kamar itu hanya diterangi lampu tidur. Dua orang pria temannya belum kembali. Saya menghempaskan tubuh di atas sofa empuk dekat jendela. Jojo mengganti kemejanya dengan t-shirt putih, setelah meminta izin lebih dulu. Ia lantas memperlihatkan surat kontrak kerja dengan pemilik stasiun radio di Jakarta dan Bali.
Tak berapa lama dua temannya muncul. Seorang wartawan radio dari Aceh, sedang yang seorang lagi tinggal di Matraman, Jakarta. Mereka teman lama. Saya berbincang-bincang soal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pria Aceh itu. “Orang sipil bersenjata tidak pernah melukai orang sipil. Mereka itu pintar. Tentara yang bodoh. Mereka membunuh rakyat,” katanya, tidak mau menyebut kata ‘TNI’. Jojo sudah tertidur pulas di atas tempat tidur berseprei putih. Dengkurnya keras. Saya tidak akan membangunkannya. Pria dari Matraman terlelap dalam posisi duduk di tempat tidur yang lain.
Wartawan Aceh itu menemani saya begadang. Katanya, jumlah uang amplop dari pemerintah daerah Meulaboh antara Rp 20 ribu-Rp 30 ribu. “Semacam uang transportlah buat wartawan. Saya kira, ini masih wajar diterima. Kalau kasus pemerasan saya belum dengar. Yang santer itu malah wartawan Medan,” ungkapnya. Menurut pria ini, gaji reporter radio minimal Rp 250 ribu.
Pukul tiga pagi saya meninggalkan hotel, menghentikan taksi, dan menikmati hari yang masih gelap. Jalanan lengang.*www.SUARAKALTIM.com/pantau.or.id/foto wanita.me.