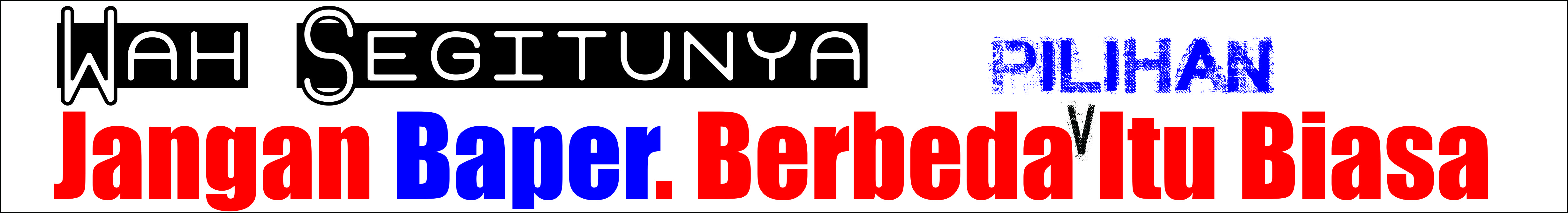Judul di atas merupakan bagian pendahuluan buku yang berjudul “Di Pedalaman Borneo: Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894” karya Dr. Anton W. Nieuwenhuis yang diterbtkan oleh Gramedia Pustaka utama. Bagian pendahuluan ini ditulis oleh Bernard Sellato, seorang pakar geologi yang banyak menulis buku tentang Pulau Kalimantan (Borneo).
Melalui penayangan bagian pendahuluan ini, kami berharap pemustaka lebih tertarik untuk membaca buku aslinya sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang lengkap dan utuh tentang Pulau Kalimantan atau Borneo. Selamat membaca! (admin/kalbariana.web.id).
Suara Kaltim – Pada abad ke-19 dimulailah tahap baru dalam sejarah kolonial, yang berakar pada situasi yang telah berkembang sejak pertengahan abad ke-18 ketika Inggris dan Belanda, dengan menggunakan kekerasan atau intimidasi, berhasil mendapat kedudukan di Borneo. Beberapa petualang, seperti Alexander Hare di Banjarmasin (1812), James Erskine Murray di Kutai (1844), James Brooke (1842) dan Robert Burns (1848) di Sarawak, berupaya mendirikan kerajaan bagi dirinya sendiri, yang satu lebih berhasil daripada yang lain. Lain halnya dengan Miiller (1825) dan Dalton (1828) yang menjelajahi Borneo atas nama negara mereka.
Walaupun sampai saat itu Belanda mengacuhkan Borneo demi pulau-pulau lain yang lebih menguntungkan, sukses James Brooke di Sarawak membangkitkan minat baru. Di bagian selatan, pada tahun 1840-an, Belanda memaksa para sultan di pesisir menandatangani perjanjian niaga, kemudian membuat mereka mengakui perwalian pemerintah Belanda. Maka eksplorasi-eksplorasi pertama ke pedalaman dapat dimulai dengan sungguh-sungguh: Schwaner di Barito, van Lijnden, Veth, dan von Kessel di Kapuas, Weddik di Mahakam.
Menjelang pertengahan abad ke-19, Belanda telah berhasil menguasai daerah-daerah pesisir dan perdagangan di muara semua sungai besar. Tentara mereka terpaksa melakukan intervensi terhadap sultan-sultan yang memberontak, seperti dalam Perang Banjarmasin (1859-1863), kemudian dalam Perang Wangkang (setelah 1870), serta terhadap suku-suku yang bersikap bermusuhan di hulu-hulu sungai, seperti suku Ot Danum dan Tebidah (di tahun 1890-an).
Sementara itu, Rajah Brooke dapat memperluas wilayahnya dengan menekan Sultan Brunei, dan juga dapat menguasai daerah pedalamannya dengan menaklukkan orang Kayan yang perkasa (Ekspedisi Besar Kayan tahun 1863) dan beberapa kelompok suku Iban (antara 1868 dan 1919). Di Sabah, Inggris menetap di Labuan pada tahun 1846. Di tahun 1860-an, Spencer St. John menjelajahi daerah Sungai Limbang dan mendaki Gunung Kinabalu, yang merupakan gunung tertinggi di antara Pegunungan Himalaya dan Irian. British North Borneo Chartered Company, yang mengambilalih kekuasaan di Sabah pada tahun 1881, terpaksa memerangi beberapa pemberontak—antara lain Mat Salleh yang kesohor. Penemuan minyak bumi dan batubara pada tahun 1880-an di Borneo mengawali integrasinya di dunia yang lebih luas.
Penguasaan niaga saja ternyata tidak lagi cukup, dan kekuatan-kekuatan kolonial sekarang membutuhkan penguasaan teritorial yang sesungguhnya, yang berdasarkan struktur-struktur administratif dan militer. Dalam rangka baru inilah ekspedisi-ekspedisi besar dilakukan pada perempat akhir abad ke-19. Tujuannya adalah wilayah-wilayah yang sampai saat itu masih merupakan “daerah putih di peta”: daerah Rejang Hulu (Hugh Low, di tahun 1880-an), Baram Hulu (Charles Hose, antara 1884 dan 1907), Mahakam (Tramp, di tahun 1880-an), dan Kapuas Hulu (Nieuwenhuis, mulai 1893 dan seterusnya).
Dasawarsa terakhir abad ke-19 juga menandai penghentian semua konflik bersenjata yang besar. Renting disebut juga, tahun 1894 diadakan perdamaian akbar Tumbang Anoi, di Sungai Kahayan Hulu, di mana para wakil dari tigapuluh suku Dayak sempat berkumpul dari Mei sampai dengan Juli 1894. Eksplorasi lebih lanjut lalu menyusul pada tahun-tahun pertama abad yang baru—oleh Knappert di kawasan Mahakam, Enthoven di Kapuas Hulu, Stolk di Sungai Busang, van Walchren di Apokayan—dan seterusnya sehingga, di tahun 1930-an, seluruh pedalaman Borneo telah jatuh di bawah kekuasaan sebenarnya dari kekuatan-kekuatan kolonial, kecuali Kesultanan Brunei yang sudah sangat menciut.
Wilayah perbatasan antara Kapuas dan Mahakam merupakan salah satu wilayah yang paling terpencil di Borneo. Di sebelah timur, daerah Mahakam Hulu, yang terisolasi oleh jeram-jeram yang sangat berbahaya, di mana suku Kayan-Mahakam, suku Busang (termasuk sub-suku Uma’ Suling dan Iain-lain), serta suku Long-Gelat (sebuah sub-suku dari Modang) menempati dataran-dataran yang subur; sedangkan suku Aoheng mendiami daerah berbukit-bukit. Di sebelah barat, daerah Kapuas Hulu, dengan kota niaga kecil Putussibau, dikelilingi oleh desa-desa Senganan, Taman, dan Kayan. Lebih ke hulu lagi, dua desa kecil: Aoheng dan Semukung. Di antara keduanya, sebuah barisan pegunungan yang besar mencapai ketinggian hampir 2000 meter didiami oleh suku nomad Bukat (atau Bukot) dan Kereho (atau Punan Keriau), serta suku semi-nomad Hovongan (atau Punan Bungan). Orang asing pertama yang mencapai dan melintasi barisan pegunungan ini adalah Mayor Miiller, pada tahun 1825. Tetapi ia tidak sempat menceritakan pengalamannya.
Georg Muller, seorang perwira zeni dari tentara Napoleon I, sesudah Waterloo masuk dalam pamongpraja Hindia Belanda. Mewakili pemerintah kolonial, ia membuka hubungan resmi dengan sultan-sultan di pesisir timur Borneo. Pada tahun 1825, kendatipun Sultan Kutai enggan membiarkan tentara Belanda memasuki wilayahnya, Muller memudiki Sungai Mahakam dengan belasan serdadu Jawa. Hanya satu serdadu Jawa yang dapat mencapai pesisir barat.
Berita kematian Muller menyulut kontroversi yang berlangsung sampai tahun 1850-an (van Kessel 1849-55, van Lijnden & Groll 1851, Veth 1854-56, Hageman 1855), dan dihidupkan kembali sewaktu-waktu setiap kali informasi “baru” muncul (Molengraaff 1895, Nieuwenhuis 1898 dan 1900, Enthoven 1903). Sampai tahun 1950-an pengunjung-pengunjung daerah itu masih juga menanyakan nasib Muller (Helbig 1941, Ivanoff 1955).
Sampai hari ini hal-hal sekitar kematian Muller belum juga terpecahkan. Memang, daerah ini tetap merupakan terra incognita sampai 1894. Namun diperkirakan Muller telah mencapai kawasan Kapuas Hulu dan dibunuh sekitar pertengahan November 1825 di Sungai Bungan, mungkin di jeram Bakang, tempat ia harus membuat sampan guna menghiliri Sungai Kapuas – pada saat itu ia berada hanya beberapa hari pelayaran dari tempat yang aman. Sangat mungkin bahwa pembunuhan Muller dilakukan atas perintah Sultan Kutai – disampaikan secara berantai dari satu suku kepada suku berikutnya di sepanjang Mahakam – dan akhirnya dilaksanakan oleh sebuah suku setempat, barangkali suku Aoheng (menurut dugaan Nieuwenhuis). Karena Muller dibunuh di pengaliran Sungai Kapuas, dengan sendirinya Sultan tidak dapat dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Bagaimanapun, ketika ekspedisi Nieuwenhuis berhasil melintasi daerah perbatasan hampir 70 tahun kemudian – pada hari nasional Perancis tahun 1894 – barisan pegunungan ini diberi nama Pegunungan Muller.
Sekarang mari kita bicarakan Dr. Nieuwenhuis.
A. W. Nieuwenhuis
Anton Willem Nieuwenhuis lahir pada 22 Mei 1864 di Papendrecht, Belanda. la belajar ilmu kedokteran pada Universitas Kerajaan Leiden dari 1883 sampai 1889. Pada tahun 1890 ia meraih gelar Ph.D. dalam ilmu kedokteran pada Universitas Albert-Ludwigs di Freiburg-im-Breisgau, Jerman, dengan tesis berjudul “Ueber haematoma scroti”.
la masuk angkatan bersenjata pada tahun 1890 dan, pada tahun 1892, ditempatkan di Sambas, Borneo Barat, sebagai perwira kedokteran berdinas pada Tentara Hindia Belanda. Residen Borneo Barat, S. W. Tromp – yang berpengalaman dan sudah pernah melakukan perjalanan di Borneo Timur – memprakarsai tahap-tahap awal eksplorasi ilmiah Borneo.
Sesudah pertimbangan panjang lebar oleh komisi ilmiahnya (Indisch Comite, yang bertindak sebagai badan penasihat), Maatschappij ter bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Kolonien (Perhimpunan untuk Memajukan Penelitian Alam di Koloni-koloni Belanda) di Amsterdam memutuskan untuk mengorganisir ekspedisi pertama. Tujuan utamanya adalah eksplorasi ilmiah Borneo Tengah, terutama daerah udik Sungai Kapuas dan cabang-cabangnya.
Ekspedisi multidisipliner pertama ini (1893-94) beranggotakan Johann Biittikofer, kurator Museum Nasional untuk Pengetahuan Alam di Leiden, untuk bidang zoologi; H. Hallier, asisten pada Herbarium Kebun Raya di Buitenzorg (Bogor), untuk bidang botani; G. A. F. Molengraaff, untuk bidang geologi; dan Nieuwenhuis, untuk antropologi fisik dan etnografi, serta sebagai dokter.
Ekspedisi dimulai pada bulan November 1893, dan berangkat dari markas ekspedisi di Semitau, tempat semua anggota akhirnya berkumpul pada tanggal 26 Pebruari 1894, menuju Sungai Mandai. Nieuwenhuis dan Buttikofer berdiam dari Maret sampai Mei 1894 di hulu Sungai Mandai, di desa Nanga Raun (yang kemudian menjadi kesohor sebagai rumah panjang terpanjang di Kalimantan Barat), di tengah suku Dayak Ulu Air (sebuah cabang dari suku Ot Danum yang sebenarnya menamakan dirinya sendiri Orung Da’an). Sementara itu, Molengraaff melakukan penelitian geologi. Lalu Nieuwenhuis dan Molengraaff kembali ke Putussibau untuk mempersiapkan perjalanan ke Mahakam.
Kontrolir Kapuas Hulu, van Velthuysen, ditunjuk untuk memimpin ekspedisi yang, di samping Nieuwenhuis dan Molengraaff, terdiri atas 19 prajurit Hindia Belanda, 5 kuli Melayu, 8 orang Iban Batang-Lupar selaku pembantu khusus Kontrolir, dan 85 orang Dayak Kayan dari Sungai Mendalam sebagai awak perahu dan pemikul barang. Mereka berangkat dari Putussibau dengan 24 sampan pada tanggal 15 Juni 1894.
Mereka melintasi perbatasan memasuki kawasan Mahakam pada tanggal 14 Juli – pertama kali seorang Eropa melakukan hal itu sejak tahun 1825. Tetapi situasi politik regional tidak banyak berubah sejak zaman Miiller. Suku-suku di Mahakam sedang mengadakan berbagai persiapan yang bersikap bermusuhan untuk menyambut mereka, begitulah berita yang disampaikan oleh seorang kurir Dayak yang baru kembali dari Mahakam. Maka, pada tanggal 15 Juli, Kontrolir memutuskan untuk kembali. Ekspedisi tiba kembali di Putussibau pada tanggal 22 Juli.
Molengraaff dan Nieuwenhuis kemudian berpisah. Molengraaff menuju ke selatan, menyeberangi pegunungan ke Sungai Samba, dan memudiki Sungai Katingan (sekarang di Kalimantan Tengah), mengadakan pengamatan-pengamatan geologi serta etnografi dan tiba di Banjarmasin pada bulan Oktober 1894. Sementara itu, Nieuwenhuis berdiam di tengah suku Kayan di desa Tanjung Karang di Sungai Mendalam selama dua bulan (Agustus – September 1894). la menganggap suku Kayan sebagai kunci ke Mahakam Hulu, sebab mereka mempunyai hubungan dengan orang Kayan lain di situ, dan ia minta mereka berjanji untuk membawanya melintasi perbatasan. Mereka menyatakan bersedia, dengan syarat ia tidak membawa pengawalan bersenjata.
Pada tahun 1894 terjadi perang Lombok. Nieuwenhuis ditempatkan di sana sebagai dokter tentara. Ia kembali ke Batavia pada 1895 dan berlayar ke Pontianak dalam bulan Februari 1896. Ekspedisi kedua diorganisir, dengan tujuan-tujuan yang sama.
Ekspedisi kedua (1896-97) dipimpin oleh Nieuwenhuis dan beranggotakan F. van Berchtold untuk koleksi-koleksi zoologi; Jean Demmeni, fotografer; Midan, koki dan pembantu pribadi Nieuwenhuis; serta dua orang Sunda dari Buitenzorg, Jaheri dan Lahidin, bertanggung jawab atas koleksi dan spesimen botanik.
Nieuwenhuis kembali berdiam di Tanjung Karang, dari tanggal 7 April sampai 15 Juni untuk lebih menguasai bahasa Kayan dan belajar Busang, yaitu bahasa perantara di Mahakam Hulu. Demmeni tiba bulan Mei, dan langsung mulai mengambil foto (direproduksi dalam buku Di Pedalaman Borneo).
Ekspedisi berangkat pada tanggal 3 Juli 1896 dari Putussibau, dengan duabelas sampan dan limapuluh awak perahu dari suku Kayan. Mengikuti jalan setapak sebelah selatan, mereka menelusuri Sungai Bungan dan Bulit, menunggu beberapa waktu di situ guna memeriksa ada tidaknya kerusuhan di Mahakam, lalu turun ke Sungai Penane dan Kaso di sebelah timur. Rombongan mula-mula berdiam di tempat suku Pnihing — yang sebenarnya menamakan dirinya sendiri Aoheng—kemudian di tempat suku Kayan-Mahakam. Seluruhnya selama delapan bulan mereka menetap di Mahakam Hulu.
Suku Kayan dari Mendalam dan kepala mereka, Akam Igau, memegang peranan sangat penting dalam kelancaran ekspedisi. Jelas bahwa, tanpa bantuan Akam Igau, Nieuwenhuis tidak pernah akan berhasil. Di seberang perbatasan, peran Kwing (atau Koeng) Irang, kepala suku Kayan-Mahakam, juga tidak dapat diremehkan.
Sesungguhnya Nieuwenhuis baru saja terjun di tengah-tengah situasi yang cukup rumit, baik dari segi politik maupun ekonomi, di mana pihak-pihak setempat perlu memanfaatkannya sebagai sarana politik baru yang tersedia bagi mereka. Suku-suku merdeka di Mahakam Hulu terjepit di antara Kesultanan Kutai dan suku Iban dari Sarawak. Sultan Kutai sedang berusaha agar mereka mengakui kekuasaannya dan memaksa mereka berdagang dengan pihaknya; dan suku Iban—terutama setelah serangan massal mereka terhadap wilayah Mahakam Hulu tahun 1885, yang menghancurkan semua desa Aoheng dan kampung besar Koeng Irang—merupakan ancaman yang selalu terbayang. Koeng, kepala suku yang paling berpengaruh di Mahakam Hulu, berjuang keras agar daerahnya tetap bebas dari Kutai, yang telah menyebabkan suku-suku di wilayah hilir Mahakam banyak menderita karena campur-tangannya. Belare’, salah satu kepala Aoheng penting yang sedang bersaing untuk menempati kedudukan terkemuka, telah memihak Sultan Kutai, yang ingin mematahkan perlawanan Koeng Irang; sementara Paron, seorang kepala Aoheng lainnya, telah bersumpah setia kepada Sultan Banjarmasin.
Mungkin sekali, Belare’, karena memihak Kutai, sempat mendalangi keresahan yang mencegah ekspedisi pertama memasuki wilayah Mahakam pada tahun 1894. Yang memungkinkan ekspedisi kedua sukses adalah Koeng Irang, karena ia segera menyadari bahwa Belanda kuat dan bisa merupakan kartu trufnya dalam persaingan politik lokal. la minta supaya Nieuwenhuis mengajukan petisi “atas nama semua suku Mahakam” kepada pemerintah Belanda agar langsung mengambilalih kekuasaan atas daerahnya. Tentu saja hal itu sangat menggembirakan Nieuwenhuis.
Perjalanan menghiliri Sungai Mahakam berakhir pada tanggal 5 Juni 1897, ketika keenam anggota ekspedisi meninggalkan Samarinda dengan tujuan Surabaya dan Batavia. Sekembalinya di Batavia, Nieuwenhuis ikut berunding dengan para pejabat pemerintah dan meyakinkan mereka untuk membiayai ekspedisi ketiga, dengan tujuan meneliti cara dan sarana untuk memperluas pemerintahan Belanda sampai ke wilayah Mahakam Hulu dan Kayan Hulu agar membentuk kedamaian dan keamanan.
Ekspedisi ketiga (1898-1900) dengan demikian terutama mempunyai maksud politik. Namun, tujuan etno-sosiologis dan medik yang sama juga dipertahankan. Kali ini pun ekspedisi dipimpin oleh Nieuwenhuis dengan anggota Jean Demmeni; J. P. J. Barth, seorang kontrolir kelas satu, yang telah mempelajari bahasa Busang; H. W. Bier, seorang topografer; Midan, koki Nieuwenhuis; Sekarang dan Hamza, dua pegawai Jawa dari Kebun Raya Buitenzorg, untuk koleksi botani; dan Doris, seorang ahli taksidermi berasal dari Jawa, untuk koleksi zoologi.
Kali ini Nieuwenhuis membawa pengawal bersenjata terdiri atas 5 orang serdadu Hindia-Belanda untuk menghadapi gerombolan-gerombolan berkelana suku Iban yang mungkin ada. la telah melakukan perjalanan khusus ke Singapura untuk membeli manik-manik kaca dan gelang-gelang gading, yang tidak dapat diperoleh di Jawa. Sekali lagi ia memutuskan untuk pergi dari Barat ke Timur, karena ia tahu bahwa Sultan Kutai, yang ingin memperluas pengaruhnya ke pedalaman, akan berusaha menghalanginya jika ia mencoba mulai dari Timur.
Ekspedisi berangkat dari Pontianak pada tanggal 24 Mei 1898 dengan tujuan Putussibau, di mana mereka tiba bulan Juni. Tetapi karena orang Kayan di Mendalam sibuk dengan kegiatan-kegiatan pertanian mereka, ekspedisi baru dapat meninggalkan Putussibau pada tanggal 18 Agustus, dengan 25 sampan bersama Akam Igau dan 110 orang, kebanyakan orang Kayan dan beberapa Bukat, Beketan, serta Punan. Tanggal 15 September rombongan tiba di Pangkalan Howong (atau Huvung), titik tolak jalan setapak utara, dari Sungai Mecai, sebuah cabang Sungai Bungan, ke Sungai Huvung di Mahakam. Di situ mereka kehabisan makanan: “rumus beras” meleset dan mereka harus mengandalkan sagu. Keadaan menjadi lebih buruk: Demmeni terserang malaria. Sesudah melakukan pekerjaan topografi singkat di daerah perbatasan, rombongan menuju desa Aoheng terdekat, di mana mereka tiba pada tanggal 24 September 1898.
Nieuwenhuis beserta rombongannya berdiam selama delapan bulan di wilayah Mahakam Hulu, mempelajari adat-istiadat serta bahasa-bahasa penduduk setempat, fauna dan flora, serta mendaki gunung-gunung untuk disurvai. Hasilnya antara lain adalah peta daerah itu – sampai 1993 ini masih yang terbaik – dan kamus Busang-Belanda karya Earth. Koleksi kerajinan rakyat juga dikumpulkan, sekarang berada di Rijks-museum vbor Volkenkunde di Leiden. (Perlu juga disebutkan koleksi yang dikumpulkan oleh Lumholtz dari daerah yang sama, sekarang di Oslo, Norwegia.)
Sampai saat itu Nieuwenhuis tidak tahu bahwa Belare’, kepala suku Aoheng itu, telah memutuskan – bahkan mencoba dua kali – untuk membunuhnya, barangkali atas perintah Sultan Kutai. Hal ini dilaporkan kemudian oleh Lumholtz, yang mengunjungi daerah ini tahun 1916. Untung saja Koeng Irang, yang tetap berusaha mendapatkan bantuan Belanda melawan Kutai dan sekutunya, berhasil menggagalkan usaha Belare’. Namun nyaris saja Nieuwenhuis mengalami nasib yang sama seperti Georg Miiller.
Akhirnya ekspedisi menghiliri Mahakam dan mencapai Samarinda pada tanggal 9 Juni 1899. Earth beserta para pengawal, dan kedua kolektor tanaman, diberangkatkan lebih dulu ke Jawa. Contoh-contoh tanaman dikirim ke Buitenzorg, dan koleksi fauna ke Museum di Leiden. Tidak lama kemudian, pada tanggal 17 Juni, Nieuwenhuis berangkat lagi menuju desa Long Blu’u, pemukiman Koeng Irang, ditemani oleh Bier, Demmeni, Doris, Midan, lima serdadu Melayu, dan empat pembantu Melayu. Dari situ ia mengorganisir perjalanan survai ke sumber Mahakam dan ke Lasan Tuyan (sebuah sela gunung di perbatasan Sarawak), mulai tanggal 30 September. Dalam perjalanan pulang dari situ, salah satu sampan terbalik di tengah jeram, untung hanya mengakibatkan kerugian material.
Perjalanan Nieuwenhuis ke Apokayan, yang telah dijadwalkan untuk tahun 1900, ternyata merupakan usaha yang rumit dan berkepanjangan. Sebagai wakil pemerintah kolonial Belanda ia melakukan kunjungan resmi kepada Sultan Kutai, yang menyatakan berkeberatan terhadap bagian kedua itu dari ekspedisinya. Dari Oktober 1899 sampai April 1900, Nieuwenhuis menantikan pembicaraan lanjutan dengan Kutai untuk mencapai hasil yang memuaskan, tetapi Sultan bertekad untuk memanfaatkan bermacam-macam alasan untuk menghalangi perluasan pemerintahan Belanda sampai ke Borneo Tengah. Lagi pula, karena suku-suku di Mahakam Hulu dan suku Kenyah di Apokayan sedang bermusuhan, ternyata sulit sekali mendapatkan pemandu untuk memudiki Sungai Boh sampai ke dataran Apokayan. Dalam bulan Mei 1900, Nieuwenhuis menem-patkan rombongannya di kamp perintis di Long Boh, di mana kemudian Bier dan Demmeni bergabung. Setelah terjadi pertengkaran, Bier diperintahkan pulang. Namun Nieuwenhuis masih harus menunggu tiga bulan lagi.
Akhirnya, bulan Juni, ada telegram: Wilayah Mahakam Hulu secara resmi telah ditempatkan di bawah pemenntahan Belanda, dan Earth akan ditugaskan di desa Long Iram sebagai kontrolir. Pada tanggal 6 Agustus, ekspedisi akhirnya bertolak dari Long Boh dengan Koeng Irang. Kali ini pun ekspedisi mengalami kekurangan beras sekali lagi di dalam perjalanan. Dengan demikian, pernyataan Smythies yang memuji Nieuwenhuis sebagai “seorang penjelajah yang efisien dan sukses” perlu dipertanyakan, karena kekurangan beras merupakan masalah yang sangat berat bagi suatu ekspedisi, yang pasti mengakibatkan situasi yang gawat.
Ekspedisi berdiam selama dua bulan di wilayah Apokayan. Banyak data dikumpulkan tentang orang Kenyah dan sejarah mereka. Karena sering diusik oleh serbuan suku Iban dari Sarawak, orang Kenyah sangat responsif terhadap tawaran Nieuwenhuis untuk mendapat perlindungan Belanda, namun mereka cemas bahwa hal itu akan menimbulkan amarah Rajah Brooke, dan mereka minta agar Nieuwenhuis menulis surat kepadanya. Rajah menjawab bahwa, karena Nieuwenhuis sudah berada di sana, ia tidak lagi ada urusan dengan Apokayan.
Ekspedisi memulai perjalanan kembali ke hilir Sungai Boh pada tanggal 4 Novem¬ber 1900, tiba di Long Iram pada tanggal 3 Desember, dan di Batavia tanggal 31 Desember 1900. Kemudian Nieuwenhuis diangkat menjadi penasihat pemerintah untuk urusan Borneo.
Beberapa tahun kemudian (1903), seorang kontrolir lain, E. W. F. van Walchren, memudiki Sungai Berau sampai di Apokayan, di mana ia berdiam enam bulan – ia kembali lagi tahun 1906 untuk menyelesaikan perseteruan antar-suku Kenyah. Dalam tahun 1906 terdengar kabar bahwa Nieuwenhuis akan kembali ke Apokayan, namun ternyata Kapten L. S. Fischer yang datang (Juni sampai Oktober 1907), mungkin untuk mempersiapkan pos perintis militer pemerintah yang akan didirikan di Long Nawang.
Sementara itu, Nieuwenhuis, yang selama perjalanan-perjalanannya tetap sehat wal’ afiat, dalam tahun 1904 diangkat sebagai gurubesar geografi dan etnologi (Land-en Volkenkunde) Hindia Belanda pada Universitas Kerajaan (Rijksuniversiteit) Leiden, Fakultas Kesusastraan dan Filsafat (Letteren en Wetenschappen). Pidatonya pada upa-cara pengukuhan, pada tanggal 4 Mei 1904, berjudul “Keadaan Hidup Bangsa-bangsa pada Tingkat Peradaban Tinggi dan Rendah”. Walaupun demikian, Nieuwenhuis di-kenal di Belanda sebagai tokoh yang sangat liberal dan progresif. Ia juga menjadi editor dari majalah ilmiah terkemuka yang diterbitkan di Leiden, yaitu Internationales Archiv fur Ethnographic. Di kemudian had, barisan pegunungan antara Sungai Baleh di Sarawak dan Kapuas Hulu diberi nama Pegunungan Nieuwenhuis.
Setelah karier akademik yang panjang sebagai pakar tentang Indonesia, Nieuwenhuis memutuskan untuk pensiun pada bulan Mei 1934. Kedudukannya diganti dalam tahun 1935 oleh J. P. B. de Josselin de Jong. Nieuwenhuis meninggal di Leiden pada tanggal 21 September 1953, meninggalkan sejumlah besar karya ilmiah. Ketika menulis obi-tuarinya, Bertling mengakui peranan perintisannya yang penting di bidang antropologi Indonesia; sementara Smythies tidak segan-segan menamakannya “Dr. Livingstone Borneo”.
Tiga Ekspedisi: Ekor dan Hasil
Ekspedisi-ekspedisi Nieuwenhuis memenuhi tujuan-tujuan politiknya yang berjangka panjang dengan menghasilkan berdirinya pax neerlandica di wilayah-wilayah ini yang diusik oleh perang dan pengayauan. Lagi pula para kontrolir, begitu mereka ditugaskan pada lokasi-lokasi di hulu sungai, mulai mengawasi kegiatan-kegiatan niaga dan memastikan bahwa suku-suku Dayak tidak ditipu secara sistematis dalam kegiatan barter mereka dengan pedagang-pedagang Melayu dan Cina. Belanda, dalam hal itu, sangat banyak mengikuti contoh yang diberikan pemerintahan Rajah Brooke di Sarawak.
Ekspedisi-ekspedisi ini menghasilkan peta-peta akurat dari daerah-daerah yang sampai saat itu belum pernah dikunjungi orang luar (termasuk pengaitan topografi pertama antara Borneo Barat dan Borneo Timur serta survai wilayah Mahakam: “daerah putih di peta” sudah tidak putih lagi), kajian-kajian linguistik (kamus Busang karya Earth), dan khasanah informasi etnografi dan sejarah mengenai suku-suku Dayak setempat.
Ekspedisi-ekspedisi itu juga mengumpulkan koleksi-koleksi zoologi dan botani yang penting; 1.500 kulit dari 209 spesies burung, 659 spesimen ikan (termasuk 51 spesies baru) dikirim ke Museum di Leiden; sekitar 2.000 spesimen tanaman dikirim ke Herbarium Buitenzorg; sejumlah contoh batu-batuan disimpan di Universitas Utrecht. Suatu spesies bulbul yang langka, tertangkap di Apokayan pada tahun 1900, diberi nama Nieuwenhuis. Sejumlah besar terbitan ilmiah didasarkan pada pengamatan dan koleksi ekspedisi-ekspedisi itu.
Pengamatan medik Nieuwenhuis, yang dimuat dalam beberapa karya tulis ilmiah, menunjukkan bahwa wabah cacar dan kolera, yang menyebar mulai dari pesisir ke arah udik, cukup lazim, sering merenggut nyawa dari seperempat sampai sepertiga penduduk kampung yang tertular. Malaria dan sifilis kronis sangat lazim di wilayah Kapuas, Mahakam, dan Apokayan. Pengamatan-pengamatan tersebut menarik perhatian pemerintah, yang tidak lama kemudian mendirikan stasiun-stasiun medis dengan dokter-dokter keliling di wilayah-wilayah itu.
Etnografi Nieuwenhuis
Melalui tulisan-tulisannya, Nieuwenhuis berjuang dengan bersikeras agar pendapat umum bahwa orang Dayak hanyalah pengayau yang kejam dihilangkan. la berkali-kali menekankan bahwa “orang Dayak yang disebut haus darah, liar, dan pengayau itu, pada dasarnya adalah penduduk bumi ini yang paling lembut, cinta damai dan cemas”. Namun, jelas bahwa tugas yang ditentukannya sendiri untuk membebaskan suku-suku di Borneo Tengah dari “sesuatu yang lebih parah dari kekafiran”, seperti dicatat oleh Smythies, tidaklah menyangkut perbudakan—walaupun memang ada budak dan mereka kadang-kadang dikorbankan—melainkan pengayauan kronis antarsuku. Bagaimanapun, Nieuwenhuis termasuk perintis yang mempopulerkan orang Dayak di kalangan ilmiah internasional.
Atas dasar pengalamannya, Nieuwenhuis mengusulkan sebuah klasifikasi kelompok-kelompok etnis di Borneo Tengah yang, menurut Smythies, nyaris tidak dapat diterima lagi saat ini. Namun, pernyataan Smythies jelas mencerminkan prasangka Sarawak yang umum nampak pada beberapa usaha—yang lebih baru—untuk mengklasifikasikan kelompok-kelompok etnis Borneo. Riset akhir-akhir ini, dengan jangkauan yang lebih luas, mungkin sekali akan menunjukkan bahwa pendapat Nieuwenhuis dalam hal ini tidak terlalu jauh meleset dari kenyataan.
Sejumlah pernyataan Nieuwenhuis tentang suku Kayan serta organisasi sosialnya, adat-istiadatnya, sikap keagamaannya, kebudayaan materialnya, dan sejarahnya pernah dipertanyakan oleh Pastor A. J. Ding Ngo, yang juga orang Kayan dan sangat akrab dengan tradisi Kayan. Memang bisa saja, karena masalah bahasa saja atau masalah lain, Nieuwenhuis salah memahami para informannya (atau sengaja dibohongi); atau, sebaliknya, bisa saja selama berdiam dengan orang Kayan pada tahun 1894 dan sesudah itu, ia mendapat data-data yang menentukan dari para informannya yang sudah lanjut usia, yang mungkin tidak diteruskan kepada generasi Pastor Ding. Tentu saja hal ini tidak dapat saya putuskan.
Akan tetapi, perihal Aoheng perlu dicatat bahwa sejumlah nama tempat dan orang tidak disalin dengan benar. Mungkin sekali, kemampuan linguistik Nieuwenhuis tidak sebaik Earth—dan kemampuan Earth tidak juga begitu hebat. Nieuwenhuis dapat berbicara sedikit bahasa Busang—dialek Uma’ Sulmg, bahasa perantara Mahakam Hulu—yang ia gunakan dalam hubungannya dengan orang Aoheng dan, karena itu, memakai versi Kayan dari nama-nama Aoheng. Di samping itu, data Nieuwenhuis tentang suku Aoheng juga menunjukkan beberapa kekeliruan kecil. Misalnya, orang Aoheng yang berdiam di Kapuas Hulu berasal dari wilayah Mahakam, bukan sebaliknya.
Namun, secara keseluruhannya, sumbangan Nieuwenhuis boleh dikatakan luar biasa. Data-datanya termasuk yang paling berharga yang pernah dikumpulkan di pedalaman Borneo oleh seorang penjelajah, dan tetap merupakan sumber utama, serta dapat diandalkan, bagi informasi etnografi dan historis tentang suku-suku di daerah-daerah yang dikunjunginya. Sayang sekali, pendekatan teoretis Nieuwenhuis jelas berbau periode awal antropologi, ketika lingkungan ilmiah masih didominasi oleh evolusionisme. “Animisme” dipandang sebagai tahap primitif pada suatu skala peradaban yang dianggap mempunyai nilai universal. Baik pendekatan yang didukung oleh aliran sosiologis Durkheim maupun aliran fungsionalis berikutnya tidak begitu dipertim-bangkan dalam karya Nieuwenhuis (lihat, misalnya, 1911 dan 1917).
Dua Buku: In Centraal Borneo dan Quer durch Borneo
In Centraal Borneo (ICB, 1900), yang ditulis dalam bahasa Belanda dan Quer durch Borneo (QDB, 1904-07), yang ditulis dalam bahasa Jerman, merupakan dua hasil utama dari ekspedisi-ekspedisi Nieuwenhuis ke Borneo. Dalam beberapa hal, keduanya merupakan buku yang berbeda, walaupun meliputi suku-suku dan subyek-subyek yang sama. ICB mengisahkan kediaman Nieuwenhuis di daerah Mendalam (Agustus sampai September 1894) dan di Mahakam Hulu (Agustus 1896 sampai Maret 1897) dan ditulis pada bulan Mei 1898, sedangkan QDB melaporkan ketiga ekspedisi secara keseluruhan. ICB terdiri atas dua jilid yang mencakup sekitar 700 halaman, sedangkan QDB, juga dua jilid, mencapai lebih dari 1.000 halaman. QDB juga berisi 170 halaman foto hitam-putih yang indah, ditambah 18 halaman foto (diwarnai dengan tangan) dari benda-benda koleksi etnografi. ICB adalah buku “populer”, dimaksudkan untuk umUm. QDB, berkat sentuhan Dr. M. Nieuwenhuis-von Uxkiill-Giildenbandt, isteri sang penjelajah, lebih bersifat “ilmiah”, dengan laporan etnografi lengkap tentang adat-istiadat dan kebudayaan material suku-suku di Borneo Tengah. QDB, dalam kata-kata Smy-thies, adalah “sungguh-sungguh suatu karya monumental”. Karya itu sayang sekali ternyata terlampau monumental bagi terjemahan dalam bahasa Indonesia ini, dan kami memilih. ICB berbahasa Belanda yang lebih ringkas. Kami juga terpaksa memutuskan untuk meringkaskan karya itu menjadi versi yang lebih singkat lagi dan lebih mudah dibaca. Versi singkat ini dilengkapi sebuah peta yang diambil dari QDB.
Akan tetapi, foto-foto yang menyertai teks diseleksi dari persediaan luas di arsip foto tentang ekspedisi-ekspedisi Nieuwenhuis di Museum Etnografi Leiden. Kebanyakan di antaranya dibuat oleh Jean Demmeni—beberapa di antaranya belum pernah diterbitkan sebelumnya—dan beberapa lagi, agaknya, dibuat oleh Nieuwenhuis sendiri. Foto-foto Demmeni termasuk yang terbaik dari zamannya. Keterampilannya belum lama ini diakui dan dipuji dalam buku yang mengabadikan karyanya dan berjudul Indonesia, Glimpses of the Past (1990). Perlengkapannya, yang diuraikan secara panjang lebar oleh Nieuwenhuis dalam tulisan-tulisannya, mencakup lensa Zeiss yang dipasang pada peti kayu berukuran 13 x 18 cm, dan film-film dengan kecepatan tinggi (untuk masa itu) termasuk film-film pertama dari jenis ini yang dipasarkan dan kemudian menggeser kedudukan plat kaca.
Foto-foto berusia 100 tahun yang disajikan di sini merupakan kesaksian visual tak terhingga nilainya, sebagai penghormatan terhadap kebesaran dan keindahan suku-suku Dayak merdeka zaman dulu dan kebudayaan mereka.
Jakarta, Desember 1993
Bernard Sellato
sumber : kalbariana.web.id
sumber foto : Buku Di Pedalaman Borneo Di Pedalaman Borneo: Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894 karya Dr. Anton W. Nieuwenhuis yang diterbtkan oleh Gramedia Pustaka utama.