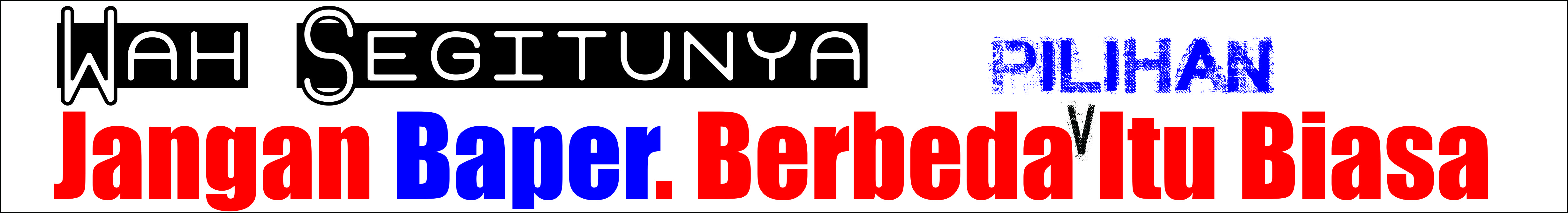Oleh Budi Setiyono
Suara Kaltim – Pertautan antara pengusaha dan penguasa bukanlah fenomena baru. Sejak revolusi, terlebih masa Orde Baru, sejumlah taipan muncul karena kedekatannya dengan kekuasaan.
Oei Jong Tjioe, seorang peranakan anggota delegasi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, mengamati persaingan sengit antara totok dan peranakan dan melukiskan bahwa kaum peranakan sedang berjuang dalam peperangan yang sia-sia.
“Terjadi perpindahan kekuasaan dari peranakan ke totok,” ujarnya sebagaimana dikutip Twang Peck Yang dalam Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950. Oey membayangkan, masa depan kelompok Tionghoa di Indonesia akan membuka banyak peluang bisnis, dan “kaum peranakan telah kalah oleh kaum totok.”
Sebagai penasihat pribadi Bung Hatta, pernyataan Oei jelas signifikan, meski bukan yang pertama.
Pada awal 1946, A.E. Abel, urusan penasehat Cina di Departemen Asia, sudah melihat kekhawatiran kaum peranakan dalam persaingannya dengan kaum singkeh (totok).
Sejak pendudukan Jepang, pembatasan dagang membuat kelangkaan persediaan barang, nilai ekspor-impor turun, dan mengacaukan rantai perdagangan tingkat perantara atau agen.
Pedagang totok berani mengambil risiko dan mencari keuntungan, terutama melalui penyelundupan dan pasar gelap. Persenjataan militer Indonesia diperoleh melalui penyelundupan ini.
Pola ini berlanjut hingga masa revolusi. Bahkan kerjasama antara pengusaha Tionghoa dan pejabat Indonesia kian jelas di masa revolusi.
“Kondisi anti-Cina dan kondisi sosial-ekonomi yang tak jelas memaksa pengusaha Cina untuk mencari perlindungan dari penguasa Indonesia.
Di sisi lain, melindungi dan bekerja sama dengan pengusaha Cina terbukti mampu menjadi sumber pendapatan bagi para penguasa,” ujar Twang Peck Yang.
Situasinya berubah ketika pengakuan kedaulatan.
Para pengusaha Tionghoa, baik totok maupun peranakan, menghadapi era baru, di mana pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan pada orang Tionghoa, juga kepentingan Belanda di Indonesia, dan meningkatkan kewirausahawan pribumi.
Pada awal 1950, Menteri Kesejahteraan Djuanda mengumumkan hanya pengusaha pribumi yang mendapat izin mengimpor barang tertentu, yang dikenal dengan sebutan Program Benteng.
Menurut Djuanda, sistem ini dibuat berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar yang memberikan hak kepada pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi kepentingan nasional dan “golongan ekonomi lemah”.
Program ini tak berjalan dengan baik. Pengusaha pribumi, karena keterbatasan kemampuan bisnis, tetap saja kalah bersaing dengan pengusaha Tionghoa.
Bahkan program itu memunculkan pengusaha rente dan “Ali-Baba”.
Menurut sejarawan Leo Suryadinata dalam Dilema Minoritas Tionghoa, banyak orang Tionghoa yang membuat perjanjian tidak resmi dengan pengusaha pribumi pemegang izin.
Yang disebut pertama menyediakan modal, menjalankan perusahaan, dan membagi keuntungan dengan yang disebut kedua.
“Praktik itu, yang dikenal sebagai sistem Ali Baba berkembag menjadi apa yang dikenal sebagai sistem cukong (atau cukongisme). Cukong adalah istilah Cina (Hokkien) yang berarti majikan, tetapi di Indonesia istilah itu digunakan untuk menunjuk pengusaha Tionghoa yang terampil bekerja sama secara erat dengan mereka yang sedang berkuasa, khususnya militer,” tulis Leo.
Pemerintah bukan tak mengakui peran kelompok Tionghoa.
Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyebutkannya dalam pidato kenegaraan saat berkunjung ke Republik Rakyat China setelah keberhasilan Konferensi Asia-Afrika di Bandung.
Seperti dikutip Leonard Blusse dalam Persekutuan Aneh, dia menyebut hubungan persahabatan yang telah berumur tua antara rakyat Indonesia dan rakyat China serta peranan penting jung-jung perdagangan China yang memberikan kebutuhan pokok bagi penduduk Nusantara dan masyarakat China perantauan yang tinggal di wilayah tersebut.
Tapi kekhawatiran pemerintah terhadap modal Tionghoa tak jua reda. Pada 1959 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 10 yang melarang para pedagang Tionghoa berusaha di daerah pedesaan.
Di sejumlah wilayah, terutama di Jawa Barat, peraturan itu diterapkan dengan paksaan. Sejumlah bisnis Tionghoa ambruk.
Pemerintah menasionalisasi perusahaan Tionghoa terbesar kala itu, Kian Gwan, milik keluarga Oei Tiong Ham.
Tak aneh, banyak orang Tionghoa, termasuk yang sudah jadi warga negara Indonesia, berbondong-bondong meninggalkan Tanah Air.
Menurut Alwi Shahab, sebagaimana dikutip Tempo, 13 Agustus 2007, pemerintah Republik Rakyat China bahkan sampai mengirim kapal ke Tanjung Priok untuk mengangkut warga keturunan Tionghoa kembali ke tanah leluhurnya.
Ketegangan kedua negara pun memuncak dan baru mendingin setelah Perdana Menteri Chou En Lai menemui Presiden Sukarno.
Diskriminasi terhadap bisnis Tionghoa berakhir ketika masa Orde Baru. Pemerintah bahkan mempromosikan modal Tionghoa dalam banyak industri; perbankan, asuransi, real estate, perkebunan, dan manufaktur.
Sejumlah pengusaha bermunculan, sebagian karena kedekatannya dengan Presiden Soeharto. Yang ternama adalah Liem Sioe Liong, atau yang juga dikenal dengan nama Sudono Salim.
Liem Sioe Liong mulai muncul pada masa Jepang. Liem, kelahiran Fukien pada 1916, datang ke Indonesia pada usia 22 tahun, mula-mula bekerja pada toko milik pamannya lalu mendirikan firma sendiri.
Kedekatannya dengan Soeharto bermula pada akhir 1950-an ketika Soeharto memimpin Divisi Diponegoro, Jawa Tengah.
Dia mendapat sejumlah monopoli (cengkih, tepung, dan lain-lain) serta berbagai fasilitas pemerintah.
Bisnisnya pun merambah hampir ke semua bidang, dari perbankan, perumahan mewah, semen, hingga makanan.
Sejak 1982, kelompok Liem merambah ke luar negeri, dengan membeli saham sejumlah perusahaan. Sebelum krisis moneter tahun 1998, kekayaan Group Salim mencapai Rp100 triliun.
Majalah Forbes bahkan pernah menobatkannya sebagai salah satu orang terkaya di dunia.
Dari keempat putranya, Anthony Salim menjadi penerusnya, termasuk menghadapi badai krisis moneter yang memukul Grup Salim.
Kini, usaha mereka masih bertahan, terutama PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT. Bogasari Flour Mills, yang merupakan produsen mie instan dan terigu terbesar di dunia.
Orde Baru bukan hanya menyuburkan bisnis mereka tapi juga, seperti ditulis Yoshihara Kunio dalam Kapitalisme Semu Asia Tenggara, membuat sebagian bisnis Tionghoa berhasil dalam persaingan dengan perusahaan multinasional.
Antara lain Suryo Wonowidjojo dengan perusahaan rokok Gudang Garam dan Tan Siong Kie dengan deterjen merek Dino dan penyedap rasa Sasa, yang mengalahkan Rinso dari Unilever dan Ajinomoto milik perusahaan Jepang.
Hubungan antara pengusaha dan penguasa tidaklah identik dengan bisnis kelompok Tionghoa.
Apa yang membuat kelompok bisnis Tionghoa lebih baik dalam kompetisi ekonomi dengan pribumi?
“Modal Cina telah lama mempunyai jaringan bisnis yang ekstensif, dan strukturnya,” tulis Yoshihara Kunio. (HIS