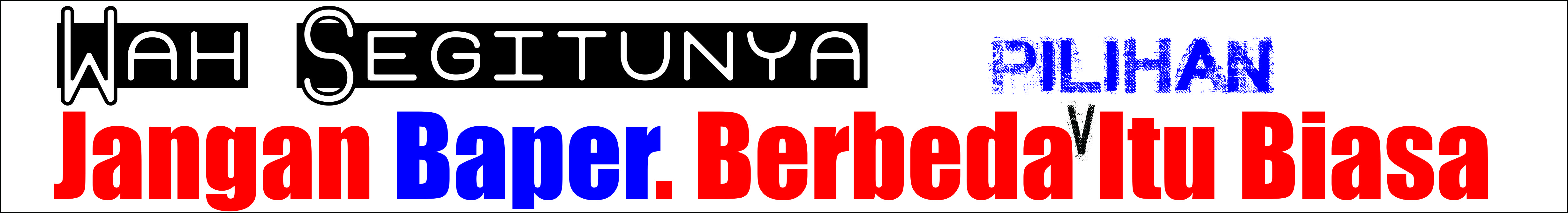Baliho politik di sebuah kota di Jawa Tengah (Foto: Imam Suripto/detiknews)
www.SUARAKALTIM.com– Ruang sosial dan fisik Indonesia dalam sebulan terakhir rasa-rasanya seperti memasuki wisata baliho, foto, dan gambar. Betapa tidak, ruang fisik masyarakat penuh dengan atribut kampanye terutama calon legislatif.
Sepintas, berbagai gambar tersebut seperti hantu yang nyaris menggantung setiap detik di hari-hari ini. Tidak salah memang. Saat ini, ruang sosial dan fisik masyarakat tunduk di bawah kekuasaan politik. Karena itu, ruang sosial dan fisik pun terpaksa mengekor di ruang politik. Semua aspek harus mengikuti derap laju politik.
Masalahnya, ketika mengamati sepintas beragam gambar, foto, dan baliho tersebut yang tampak bukan kesungguhan komitmen keterwakilan. Yang terlihat bukan kemauan memperbaiki kondisi fisik dan sosial masyarakat. Yang dibaca ialah realitas narsistik yang terus ditunjukkan dengan amat vulgar.
Masyarakat Foto
Susan Sontag (1977) pernah mengatakan bahwa dunia saat ini merupakan dunia yang dikuasai foto. Disebutkan demikian karena setiap kegiatan harus berakhir dengan foto. Persoalan kualitas pertemuan atau apa pun, sejauh telah diisi dengan foto bersama maka soal itu sama dengan tuntas.
Bagi saya, hampir semua pernyataan Sontag mendapat kepenuhannya di ruang politik lokal dan nasional kita saat ini. Sekadar menyebut satu-dua contoh, arisan, rapat koordinasi, sosialisasi politik, apa pun dan di mana pun menjadi belum cukup kalau tanpa diakhiri dengan foto bersama.
Setiap pertemuan, diskusi, kumpul keluarga bahkan pada level ujian skripsi mahasiswa pun semuanya harus diakhiri dengan foto bersama. Saya tidak mengatakan bahwa foto itu tidak penting. Yang ingin dikatakan adalah bahwa ketika foto menjadi tujuan akhir dan bukan sarana atau alat maka pada titik itu, mengikuti Sontag, generasi kita menjadi generasi foto, termasuk generasi politik kita.
Menarik untuk mengamati realitas politik kita akhir-akhir ini. Di berbagai tempat seperti lorong-lorong, jalan, jembatan, gang dan sebagainya foto dan baliho bakal calon legislatif bertebaran tanpa bentuk, aneh, dan kadang memuakkan. Disebut demikian karena pencari kekuasaan seperti keluar dari singgasananya dan menemui masyarakat pada momen politik saja. Melalui media ini, banyak elemen berteriak.
Fenomena seperti ini sebetulnya menggambarkan orang yang tidak percaya diri. Selain tidak percaya diri, fenomena yang sama menerangkan bahwa memang selama ini pencari kekuasaan itu tidak pernah berbuat sesuatu yang baik untuk masyarakat. Maka, ketika momen politik tiba mereka harus mengeluarkan semua energi yang dimiliki, bahkan sampai pura-pura senyum sekalipun, agar rakyat pemilik sah kekuasaan dapat melihat serta menjatuhkan pilihan.
Generasi Baliho
Munculnya generasi baliho dapat diterangkan dengan teori transformasi politik. Justin Lewis, Sanna Inthorn, dan Karin Wahl-Jorgensen dalam Citizens orConsumers? What the Media Tell Us about Political Participation (2005)menyebutkan bahwa partisipasi politik warga saat ini sangat rendah. Persoalannya adalah dalam jagat politik kontemporer, warga telah berubah wujud menjadi konsumen.
Ketika terjadi perubahan seperti itu maka pemain politik sebisa mungkin mempengaruhi warga dengan beragam cara. Penggunaan media baliho menjadi salah satu contoh praktisnya. Asumsi politiknya dapat dijelaskan dengan sangat mudah.
Ketika warga dilihat sebagai konsumen, maka ruang untuk menipu dan manipulasi dapat dilakukan. Harus dipahami bahwa dalam dunia ekonomi modern, untung dan keuntungan serta akumulasi modal menjadi moral utama. Akibatnya, setiap usaha politik diarahkan untuk mencapai tujuan ekonomis itu.
Karena sifatnya demikian maka kesejahteraan rakyat pasti diabaikan. Selanjutnya, untuk mendapatkan kekuasaan politik, para pemain politik harus bisa mengelabui masyarakat dengan janji dan tipu daya. Usaha itu harus dimulai dari diri pemain politik itu. Itulah yang menyebabkan mengapa gambar elite kekuasaan di foto dan baliho “terlampau sempurna”. Sederhananya, mereka harus dilihat seperti bayi tanpa dosa dan malaikat pembawa berkat.
Politik kita memang kental dan dekat dengan baliho. Dalam studi sosiologi media, ketika realitas asli disulap sedemikian rupa menjadi realitas simbolik maka terjadilah hiperrealitas. Di ruang hiperrealitas itu, yang substansial akan diabaikan untuk diubah menjadi serba artifisial tanpa makna.
Janji politik “untuk kepentingan masyarakat banyak” dalam baliho akan segera diubah menjadi “untuk diri dan keluarga sendiri” dalam kenyataan nanti. Amat narsistik sifatnya. Realitas narsistik bisa dilihat secara gamblang di sana. Sebagian besar foto, gambar, dan baliho diisi dengan foto diri, partai, dan nomor urut. Ditambah embel-embel tulisan coblos nomor sekian. Selesai.
Soal seperti apa visi dan misi keterwakilan dia besok jika dipiliha rakyat, tidak pernah disertakan. Bisa dipahami memang. Sebab, sistem politik kita memang mementingkan partai ketimbang visi keterwakilan seseorang.
Ada yang berargumentasi bahwa keterwakilannya bisa direalisasikan ketika sudah dipilih nanti. Betul. Masalahnya, ketika hanya menunjuk orang dan partai pendukungnya, tanpa mengetahui rekam jejak, visi-misi, dan catatan prestasi yang dimiliki seseorang, bukankah kita tetap saja memilih kucing yang bersembunyi di dalam karung?
Inilah dosa sistem kita. Kita tidak pernah menguji para caleg secara benar dan tepat. Yang terjadi selama ini ialah sejauh seseorang memiliki jaringan politik dan sedikit masuk ke arena politik karena berbagai pertimbangan, entah ekonomi maupun sosial, orang tersebut laik dicalonkan oleh partai tertentu.
Dengan demikian, proses rekrutmen calon anggota partai perlu digugat dan laik didiskusikan. Sebab, semua caleg yang akan menjadi wakil rakyat berawal dari proses politik yang disebut input. Idealnya, di sana, caleg yang ingin bertarung harus diukur dan diuji dengan sangat ketat.
Realitas itu tidak terjadi di Indonesia. Proses instan lebih sering digunakan dalam proses kandidasi di Indonesia. Yang terjadi kemudian ialah kuota melampaui kualitas. Ini soal. Maka, masyarakat jangan mudah percaya dan terprovokasi memilih mereka yang menebarkan senyum yang pura-pura menawan itu. Kini saatnya berpikir kritis dan bertindak bijak. Lacak dan amati rekam jejak para calon wakil rakyat itu.
* Lasarus Jehamat dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang