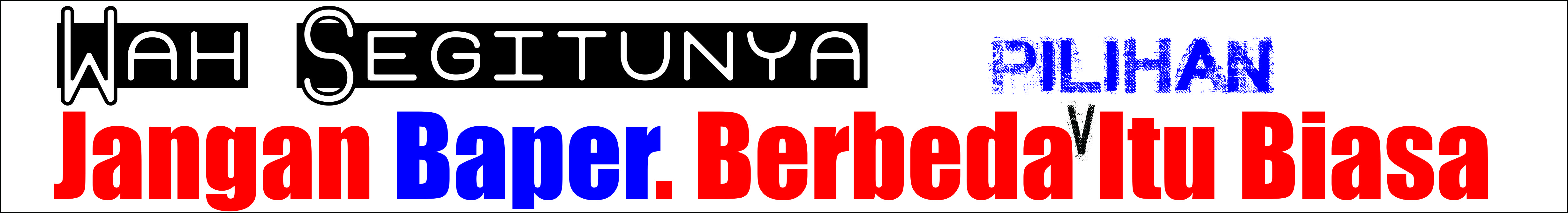oleh : Mussidi
- Haji Morshidi bin Haji Marsal, akrab dipanggil Mussidi, dilahirkan pada tanggal 22 Juni 1955 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam (lengkapnya profil sastrawan-sastrawati Borneo)
SETELAH mengunci pintu aku pun melangkah dengan tenang. Aku memandang ke atas dan mendapati langit begitu cerah, tidak ada tompok-tompok awan hitam di mana-mana. Cuaca baik sekali untukku bersiar-siar sambil membeli-belah sedikit di ibu kota.
Sebaik-baik saja aku tiba di pintu pagar seorang posnita menghulurkan seberkas surat untukku. Posnita ini bertelanjang bulat. Aku tercengang. Mataku terbelalak besar. Cuma kepalanya ditutupi topi pos. Posnita ini juga terpegun memandangku. Kemudian ia menjerit kuat dan panjang. Ia melarikan diri ketakutan sambil terus menjerit-jerit. Jarinya menunjuk-nunjuk ke arahku.
Orang ramai berkejaran. Seorang demi seorang mereka muncul dan berkumpul di depanku. Mereka semuanya bertelanjang bulat.
Aku tercegat di sini berpakaian lengkap. Aku tidak berdaya untuk maju atau mundur. Mulutku terlompong dan daguku terasa seakan-akan hendak jatuh ke tanah di hujung kasutku yang berkilat bersih.
Mereka memandang pakaianku dari atas ke bawah. Aku terikut-ikut memandang diriku. Mencari-cari apa yang mereka cari. Kemejaku dan kasutku berwarna putih. Seluar panjangku berwarna kelabu dan tali pinggangku berwarna hitam. Aku memandang mereka semula.
“Awas,” ada orang memekik. “Jangan biarkan ia bebas!”
Seorang lelaki botak mara dengan bengis mengacah-acahkan kayu panjang padaku. “Undur! Undur!” katanya. “Cepat!”
Aku mengelak tapi enggan berundur sambil cuba-cuba memahami apa yang sedang berlaku. Ia tidak berhak melakukan aku seperti binatang. Ancamannya bertambah galak. Hujung kayu panjang ini mengotori kemejaku yang putih bersih. Aku memandang lelaki botak ini dengan tajam. Inilah kali pertama aku melihat seseorang yang betul-betul bertelanjang dari atas kepala ke hujung kaki.
“Cepat undur!” jerkahnya menggertakku dengan kayu panjang ini lagi. “Awas kau! Awas!”
Orang kian bertambah ramai berkerumun jadi penonton. Lelaki, perempuan, anak-anak kecil, bapak-bapak, emak-emak, mereka semuanya bertelanjang bulat.
Aku memandang lelaki botak ini lagi. Bulu keningnya tidak ada. Begitu juga bulu matanya. Misai, janggut dan bulu-bulu lain di tubuhnya semua dicukur licin. Otot-otot tubuhnya menegang. Ia terus mengacu-acukan kayu panjang ini.
“Hei!” aku menyergahnya dan maju setapak.
Ia terkejut. Hampir-hampir saja kayu di tangannya ini terjatuh. Tubuhnya yang telanjang ini berkilat dipancar matahari.
Lelaki botak ini bertambah bengis. Aku terpaksa berundur. Tiba-tiba tiga biji kerikil berturut-turut mengenai kepalaku. Orang ramai yang bertelanjang ini mula mara ke arahku. Mata mereka bersinar dengan ancaman. Mereka bertambah berani apabila melihat aku berundur. Sebiji batu besar mengenai bahu kiriku. Mereka menyergah hiruk-pikuk dan mula melempar batu ke arahku. Peluh dingin mengalir di tengkukku apabila aku terlihat seorang lelaki tua mara membawa buluh runcing. Terbayang di kepalaku betapa buluh runcing ini akan menembusi perutku. Mereka bersungguh-sungguh hendak menggeronyokku. Dengan cepat aku berpaling dan berlari menuju ke pintu rumah. Tanganku yang geraentar akhirnya berjaya memasukkan kunci pada lubangnya. Pintu ini kubuka. Aku masuk dan menguncinya semula dari dalam. Jantungku berdegup pantas. Aku tercungap-cungap.
Aku mengintai ke luar melalui lubang kunci. Mereka semua masih tercegat di situ bertelanjang bulat.
Kemudian aku duduk bersandar pada daun pintu melepaskan lelah dan menenangkan perasaan. Aku menyeka peluh dan mengurut-urut dadaku yang sesak.
Riuh-rendah di luar beransur-ansur reda. Aku mengintai melalui lubang kunci: seorang demi seorang orang-orang yang bertelanjang bulat ini mula pergi. Cuma tinggal beberapa orang saja lagi yang masih berjaga-jaga.
Lelaki botak masih dalam keadaan berwaspada. Lelaki tua berbuluh runcing sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita muda yang mencatat-catat sesuatu di buku notanya. Aku terfikir betapa hodohnya lelaki tua ini tanpa segan silu menggaru-garu pangkal pahanya yang dihidapi sejenia penyakit kulit. Dan wanita itu kenapa ia mempamerkan anggota-anggota peribadinya seperti itu?
Kenapa mereka semuanya bertelanjang?
“Hei!” lelaki botak memekik. “Jangan kaucuba mengacau sesiapa lagi!”
“Kami tidak menyekat kebebasanmu!” laung lelaki tua. “Tapi jika kau berlagak bijak dari kami semua dan mengganggu kententeraman awam, kami akan bertindak!”
Jadi inilah kesalahanku: aku telah berlagak bijak dan mengganggu ketenteraman awam. Tapi posnita itulah yang memekik-mekik tidak tentu pasal – menjerit-jerit seperti dirasuk setan. Akibatnya aku yang nyaris-nyaris kena bunuh.
Aku mengintai lubang kunci. Mereka semua sudah pergi. Keinginanku untuk bersiar-siar di ibu kota sudah jadi tawar. Aku ragu-ragu tentang keselamatan diriku. Tapi aku terpaksa juga keluar untuk membeli sesuatu.
Kubiarkan sejam berlalu. Apabila kurasakan keadaan sudah mengizinkan bagiku aku pun keluar.
Dengan membaca Bismillah aku melangkah dengan hati-hati. Jika aku terlihat seseorang menuju ke arahku aku akan cepat-cepat mencari tempat bersembunyi – di balik pokok kayu atau rumpun bunga. Apabila orang ini sudah lewat dan aku hanya dapat melihat belakangnya telanjang aku pun keluar dari tempat persembunyianku lalu meneruskan perjalanan.
Dalam keadaan aku takut-takut kepada mereka inilah aku mula menyedari bahawa sebenarnya mereka juga takut padaku. Bukankah langkah-langkah mereka jadi ragu-ragu apabila dari jauh mereka sudah terpandang padaku? Jika mereka takut padaku, mengapa aku mesti takut pada mereka?
Aku berjalan tanpa bersembunyi-sembunyi lagi.
Dari jauh aku terlihat seorang lelaki bersama teman wanitanya: kedua-dua mereka bertelanjang bulat. Apabila saja terpandang padaku mereka dengan tergesa-gesa menyeberang jalan. Aku dapat merasakan bahawa mereka tetap mengawasi gerak-geriku. Langkah-langkah mereka menjadi pantas. Mereka seolah-olah hendak berlari tapi merasa malu pula hendak berlari.
Kemudian dengan serentak mereka memandang padaku. Selepas ini dengan segera pula mereka berpaling semula memandang ke depan.
“Ia sepatutnya tidak dibenarkan merayau-rayau,” aku terdengar wanita ini berkata. “Bahaya. “
Teman lelakinya menganggukkan kepala.
“Kita sudah cukup senang dengan keadaan kita selama ini – tanpa ada orang yang memandai-mandai sepertinya,” sambung wanita ini. Ialah wanita pagi tadi yang mencatat-catat sesuatu di buku notanya. Rambutnya yang hitam dan panjang menutupi belakangnya hingga ke paras punggung. “Kita tidak mahu ada bidaah sepertinya merayau-rayau bebas. Barangkali ia mahu mencari pengaruh dan merobah keadaan. Ia kira ia lebih bijak dari kita semua dengan berkeadaan seperti itu. “
Teman lelakinya terus-menerus menganggukkan kepala. Ia kelihatannya amat senang berbuat begitu.
Aku ingin hendak menerangkan bahawa aku tidak berniat jahat terhadap sesiapa dengan berpakaian lengkap. Aku juga mahu memberitahunya bahawa aku sebenarnya merasa amat bingung melihat orang bertelanjang lebih-lebih lagi pada wanita muda yang berbentuk tubuh sepertinya.
Tapi mereka sudah pergi jauh dan aku hanya sempat tercegat sebentar dengan mulut yang terbuka luas tanpa suara.
Aku meneruskan perjalananku dan sampai di pusat membeli-belah. Ketika aku hendak masuk ke sebuah pasar raya tiba-tiba langkahku dihalangi oleh seorang lelaki berbadan tegap.
“Keluar!” jerkahnya. “Keluar!”
“Aku hendak membeli sesuatu,” kataku dengan lembut dan berbahasa.
“Baiklah,” katanya dengan kasar. “Tapi lakukan segera!”
Ia menggiringku masuk dan mengawasi setiap langkahku.
Aku jadi tumpuan perhatian setiap orang di sini tapi mereka mengekalkan jarak yang selamat di antara diri mereka dengan diriku.
Aku memandang sekelilingku. Para pembeli, jurujual, gadis-gadis yang manis dan pemuda-pemuda yang tampan mundar-mandir ke sana ke mari semuanya bertelanjang bulat. Mereka membalas pandanganku dengan jijik, ragu-ragu, curiga dan seperti berprasangka.
Aku memandang lelaki tegap yang menggiringku. Aku merasa malu dan cepat-cepat mengalihkan mataku ke arah lain; aku terpandang seorang nenek tanpa sehelai benang menutupi tubuhnya.
“Cepat!” perintah lelaki tegap di sisiku. “Jangan berlengah-lengah lagi!”
Aku memberanikan diri bertanya padanya apakah ia tidak merasa malu.
“Apa?” katanya.
“Apakah Encik tidak merasa malu?” ulangku.
“Malu?” ia menyoal kembali. “Malu kerana apa?”
Ia menggaru-garu pangkal pahanya.
“Sudah!” katanya. “Jangan banyak cakap! Beli apa yang kaumau beli!”
Aku sudah tidak ingat apa yang hendak kubeli. Aku memberitahu padanya bahawa syaitan terkutuk telah telah menyebabkan aku terlupa benda apa yang henddk kubeli. Lelaki berbadan tegap ini jadi marah. Dengan kasar aku ditolak-tolaknya ke depan menuju pintu terdekat dan aku ditendangnya keluar.
“Pergi!” jerkahnya.
Aku pergi jauh. Ketika inilah aku merasa sangat-sangat berharap akan bertemu seseorang yang berpakaian lengkap dan kemas sepertiku atau seorang sahabat yang sudi menerangkan kepadaku tentang apa yang sebenarnya sedang berlaku. Kenapa setiap orang bertelanjang bulat? Kenapa mereka menayangkan perhiasan-perhiasan peribadi mereka? Dan kenapa mereka memandangku seolah-olah mereka memusuhiku?
Aku berjalan terus dan memasuki sebuah kedai kopi. Aku duduk berehat-rehat di sini. Tiada sesiapa yang mahu melayaniku. Lama-lama aku jadi gusar. Tapi cepat-cepat menyedarkan diri bahawa hakku untuk marah-marah sudah tidak ada kecuali barangkali jika aku bersedia menanggalkan seluruh pakaianku dan bertelanjang bulat seperti orang ramai.
Aku memanggil seorang gadis pelayan dengan lembut. Ia datang menghampiriku dengan ragu-ragu dan takut.
“Berikan aku Coke,” kataku dengan mesra.
Pergerakan orang ramai di kedai kopi ini macam terbantut setengah jalan melihat gadis pelayan membawa minumanku dengan terketar-ketar. Tangannya seolah-olah saja menjadi terlalu pendek untuk menghulurkan dan meletakkan minuman ini di depanku.
Aku memandangnya dari atas ke bawah. Ia memiliki tubuh yang sedap dipandang. Kulitnya halus kuning langsat. Aku merasa amat sayang pada tubuh seperti ini.
Aku mengambil minumanku ini. Ia cepat-cepat menarik tangannya. Ia pergi tergesa-gesa dengan muka yang amat lega.
Aku segera menghabiskan cokeku dan terus berangkat.
Tiba-tiba gadis pelayan ini tercegat di depanku. Aku merasa hairan bagaimana ia yang pada mulanya takut-takut tiba-tiba saja menjadi berani seperti ini. Matanya menusuk tajam ke dalam mataku. Ia menghulurkan tangannya. Tangan ini sudah tidak terketar-ketar seperti tadi.
“Wangnya mana?” katanya dengan lantang.
Aku menerangkan padanya bahawa syaitan yang terkutuk telah menyebabkan aku terlupa hendak membayar. Aku meletakkan beberapa keping wang kertas di atas tapak tangannya yang tertadah ini. Wang ini lebih dari cukup. Kataku selebihnya ambillah untuk tips.
“Terima kasih,” katanya dengan amat lembut dan dengan senyuman yang manis.
Aku cepat-cepat beredar.
Matahari memancar terik. Bayang-bayang membuntar di tapak kakiku. Aku merasa rimas dan mulai berpeluh. Hari sudah tinggi.
Langkah-langkahku terhenti apabila bahuku ditepuk dari belakang.
“Selamat tengah hari!”
“Selamat tengah hari!” jawabku segera sambil berpaling menghadapi orang ini: sahabatku bersama teman wanitanya. Mereka berdua juga seperti orang lain – bertelanjang bulat.
“Kami sedang mencari-carimu,” kata sahabatku ini. “Tidak baik kau merayau-rayau seperti ini. “
Ia mamandangku dari atas ke bawah penuh simpati.
“Biar kami hantarkan kau pulang,” katanya. “Keretaku tidak jauh dari sini. Mari!”
Ia memegang pergelangan tanganku kejap-kejap seolah-olah ia takut aku akan terlepas lari ke mana-mana. Aku merasa nyanyuk apabila ia mengatakan bahawa dalam keadaan yang seperti ini aku sangat-sangat memerlukan seseorang untuk menjaga diriku.
Di sepanjang perjalanan di dalam keretanya ini, aku memejamkan mata kerana terlalu letih.
Aku terdengar sahabatku ini bercakap-cakap pada teman wanitanya. Aku tidak dapat menjangkau hujung pangkal perbualan mereka: semuanya kedengaran terlalu asing.
Tiba di rumah aku membuka kasutku. Mereka gembira melihat aku membuka kasut. Aku membuka bajuku kerana panas. Mereka bertambah gembira melihat aku membuka bajuku ini. Kemudian mereka menunggu dengan diam. Aku tidak akan membuka seluarku.
Kuajukan soalan yang bertubi-tubi kepada mereka.
Kenapa orang ramai termasuk mereka berdua bertelanjang bulat? Apakah mereka tidak malu? Atau nilai-nilai lama sudah dimansuhkan oleh nilai-nilai baru dan akulah yang ketinggalan zaman dan tidak tahu menyesuaikan diri? Apakah aku masih berada di dalam abad kedua puluh atau kini sudah abad kedua puluh ribu dan kiamat sudah hampir tiba?
Sahabatku ini tidak menjawab soalan-soalanku tapi ia menjelaskan tentang keadaan diriku yang berbeza dari keadaan dirinya dan masyarakat keseluruhannya.
Ia seorang sahabat yang suka berterus terang.
“Salahmu sendiri juga,” katanya. Ia berpeluk tubuh memandangku dengan serius. Rambutnya nipis disikat lurus ke belakang.
“Apa yang mesti kubuat?” tanyaku.
“Kau mesti mengikuti orang ramai,” katanya. Ia mempunyai mulut yang besar dangan bibir yang sederhana bentuknya. “Jika mereka bertelanjang bulat, kau juga mesti bertelanjang bulat. “
Mereka memberi beberapa cadangan dan nasihat padaku. Kemudian mereka meminta diri dan pergi.
Apabila mereka sudah tiada aku baru teringat apa yang hendak kubeli tadi.
Aku memperkukuhkan tekad dan bersiap-sedia hendak keluar lagi: kutanggalkan seluarku – aku bertelanjang bulat.
Kupejam mata. Pintu akan kubuka dan aku akan melangkah keluar. Kemudian mata akan kucelikkan.
Malu itu cuma perasaan. Dan peduli apa dengan perasaan!
Bagaimana, tiba-tiba terbayang di kapalaku, bagaimana sekiranya ketika aku mencelikkan mata ini kudapati setiap orang di depanku semuanya berpakaian lengkap dan cuma aku seorang saja yang bertelanjang bulat?
Aku duduk tersandar di daun pintu. Aku tidak jadi melangkah keluar. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku tercungap-cungap.
Setelah perasaanku reda aku merapatkan mataku ke lubang kunci.
Tidak ada sesiapa di luar. *
(Borneo Bulletin)
foto ilustrasi/lukisan Edvard Munch’s “Self-Portrait in Hell” (1903). Credit Munch Museum/Artist Rights Society (ARS), New Yor