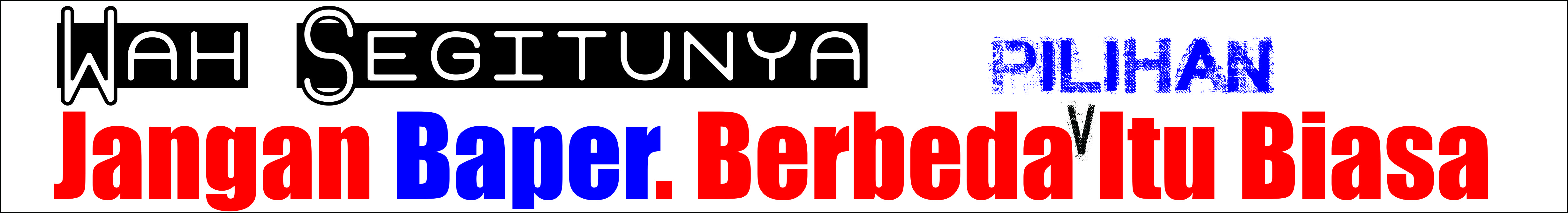Anderson kenal Indonesia, fasih beberapa dialek sini, rutin membaca suratkabar Indonesia, dan menariknya sering menyebut Kompas sebagai suratkabar Orde Baru yang sempurna.
Ini sindiran terhadap Kompas. Tapi se-orde-baru-orde-barunya Kompas, kalau asumsi Anderson mau dipakai, mungkin tak se-orde-baru Pikiran Rakyat –suratkabar terbitan Bandung yang mendominasi media Jawa Barat. .
Isi perut Pikiran Rakyat (selanjutnya disingkat PR) biasa saja. Tak ada kecenderungan untuk berhadapan secara diametral dengan kekuasaan. Lebih-lebih mengutuki pemerintah setempat. Dari dulu sampai sekarang, pemberitaan-pemberitaan PR tetap datar, santun, afirmatif, kadang-kadang berkesan melulu cari aman.
Galibnya suratkabar cari aman, produk berita omongan (talking news) dapat ditemukan di hampir setiap halaman berita. Isunya bisa politik, hukum, ekonomi, atau pendidikan. Bahkan pemberitaan kriminal sekali pun, yang sebenarnya bisa dilakukan secara on the spot, acap ditulis setelah mendapatkan kutipan dari pejabat yang dianggap berwenang –entah polisi, jaksa, atau hakim.
Kalau dibilang lebih sempurna dari Kompas, itu karena PR terang-terangan menyebut dirinya suporter Orde Baru. Konstelasi ini barangkali bisa dijejak ke tulisan Muhammad Ridlo ‘Eisy berjudul PR, Bacaan Utama & Pasar Jabar.
“Masyarakat Jabar,” kata bekas wakil redaktur pelaksana PR itu, “mengenal Fikiran Ra’yat sejak 1932, saat Bung Karno sering menulis gagasannya tentang kemerdekaan. Walaupun PR sekarang bukan kelanjutan Fikiran Ra’yat dahulu, sikap partisan tetap melekat dalam diri management-nya. PR sekarang ini didirikan 24 Maret 1966 adalah salah satu koran pendukung lahirnya Orde Baru.”
Sebagai pendukung Orde Baru, PR merapat secara total ke tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), satu-satunya organisasi kewartawanan di masa rezim Soeharto, yang notabene jadi salah satu mesin politik Orde Baru. Seluruh awak redaksi, dari pemimpin redaksi sampai reporter pemula, dilesakkan ke situ. Bukan cuma anggota, apalagi sekadar pelengkap belaka, mereka mendominasi struktur kepemimpinan PWI Jawa Barat, dari kepala, leher, sampai kaki. Dominasi ini melebar ke berbagai daerah tingkat dua lewat peran para korespondennya.
Mereka yang coba-coba menyebal dari sistem, dapat dipastikan akan menenun akibatnya. Wartawan Herry Dim, misalnya, beberapa saat setelah menghadiri pertemuan jurnalis di Sirnagalih, Bogor, pada 1994 —yang merupakan titik awal terbentuknya Aliansi Jurnalis Independen, organisasi wartawan yang menolak korporatisme Orde Baru lewat PWI—belakangan hilang dari masthead redaksi. Ia terlempar ke sektor pekerjaan nonjurnalistik. Hari-hari berikutnya ia habiskan buat melukis dan membuat puisi.
Kesempurnaan koran pagi tersebut juga bisa dilihat dari riwayat pendiriannya. Snapshot sejarah memperlihatkan dengan jelas, PR tumbuh dan berkembang di bawah asuhan militer, pilar utama kekuatan Orde Baru. “PR mah digedekeun Kodam (PR itu dibesarkan Kodam),” kata Eddy Djunaedi, seorang wartawan tua yang pada 1960-an bekerja buat Sipatahoenan, koran terkenal di Bandung.
PADA 1 Oktober 1965 Angkatan Darat bangkit melawan kekuasaan Presiden Soekarno yang kekiri-kirian. Hari itu juga pers langsung kena berangus. Sore itu Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, penguasa militer Jakarta, menutup semua suratkabar, kecuali Berita Yudha dan Angkatan Bersendjata, dua media subordinan militer. Koran-koran yang kemudian terbit dengan izin khusus, diharuskan merujuk kantor berita Antara dan Pemberitaan Angkatan Bersendjata. Tindakan ini segera diikuti panglima-panglima daerah lain di Indonesia. Benih-benih Orde Baru—suatu rezim kekuasaan di bawah kepemimpinan jenderal Soeharto, yang mengekang kemerdekaan warganya untuk berekspresi—mulai bersemi di Indonesia.
Bandung, Januari 1966. Sejumlah wartawan yang kehilangan medianya menemui Ibrahim Adjie, panglima Kodam (Komando Daerah Militer) Siliwangi, Jawa Barat. Mereka antara lain: Sakti Alamsjah, Amir Zainun, Soeharmono Tjitrosoewarno, dan Atang Ruswita. Alamsjah dan kawan-kawan sebelumnya dikenal sebagai wartawan PR, koran yang diterbitkan Djamal Ali pada 1950-an.
Hati mereka lega. Adjie mengizinkannya untuk menerbitkan Harian Angkatan Bersendjata, sebuah suratkabar filial Angkatan Bersendjata di Jawa Barat. Restu Adjie tertuang dalam sebuah surat keputusan. Tepat di hari peringatan peristiwa heroik Bandung Lautan Api, atau sekitar tiga bulan setelah pertemuan, sebuah koran baru meluncur ke hadapan publik. Edisi perdana Harian Angkatan Bersendjata, 24 Maret 1966, dicetak tiga ribu eksemplar. Tebalnya, tak lebih empat halaman.
Penerbitan awal Harian Angkatan Bersenjata lahir dari semangat titan. Jangankan kantor, mesin ketik pun mereka tak punya. Apalagi mesin cetak. Mereka bekerja di mana saja. Hari ini di kantor x, besok di kantor y, lusa nèbèng di kantor z. Mereka bekerja tanpa gaji. Satu-satunya “honor” yang mereka peroleh adalah dari penjualan kertas sisa, yang mereka timbun saban hari untuk dijual di akhir bulan. Seluruh awak redaksi mendapat jatah yang sama. “Semangat persaudaraan begitu tinggi. Dengan semangat itulah kami menghadapi situasi serba kekurangan,” kata Soeharmono Tjitrosoewarno kepada saya Mei lalu.
Semangat itu terus menyala dan menemani hari-hari keras mereka: mencari berita dari pagi sampai siang, mengetik mulai sore, bergulat dengan timah panas letter press malam hari, kemudian menggelindingkan gulungan kertas di ruas Jalan Asia-Afrika, dan kadang-kadang selepas subuh ikut mengedarkan koran. Tanpa disadari, mereka hampir setahun membanting-tulang.
Di depan hidung mereka, sebuah perubahan baru saja terjadi. Departemen Penerangan telah mencabut aturan yang mengharuskan suratkabar yang bergandul pada partai politik. Segera saja awak Harian Angkatan Bersenjata mendatangi lagi “orangtua asuhnya.” Ketika itu, tongkat komando militer Siliwangi sudah beralih ke tangan Letnan Jendral HR Dharsono. Oleh HR Dharsono, afiliasi Harian Angkatan Bersenjata dilepaskan dari induknya. Nama koran diganti jadi Pikiran Rakyat.
Ketergantungan mereka kepada militer putus dengan sendirinya. Namun, jabang bayi PR tetap mendapatkan belaian tokoh-tokoh militer setempat secara pribadi. Ibrahim Adjie dan bekas bawahannya Nawawi Alief adalah beberapa nama yang dapat disebut di sini. Bahkan karikatur Mang Ohle, yang jadi trade mark suratkabar itu, sampai kini dibuatkan Tedi MD, seorang tentara berpangkat sersan mayor. Sedangkan manajemen dikendalikan Kapten Affandi.
Nawawi Alief, bekas juru bicara Komando Daerah Militer Siliwangi, punya catatan tersendiri dalam sejarah PR. Ia dianggap salah seorang yang punya jasa besar, dan karenanya sampai kini masih menguasai saham pendiri dengan ahli waris Rosihan S. Alief, anaknya. Alief seniorlah yang mengusahakan pinjaman modal awal PR. “Modal awalnya 600 ribu atau enam juta. Saya lupa-lupa ingat. Tapi mungkin enam juta,” kata Eddy Djunaedi, eks wartawan Sipatahoenan. “Koran saya juga pernah ditawari.”
Modal itulah, menurut Djunaedi, yang memainkan peran penting buat PR di masa bayi. “Tak ada modal-modal lain. Cuma itu.”
Sebagai “anak kolong”, ini sebutan buat mereka yang dibesarkan dalam tangsi militer, PR dimungkinkan dapat tumbuh dan berkembang tanpa gangguan berarti, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti payung yayasan dengan sebuah perseroan terbatas. Itu tahun 1973 ketika notaris Noezar SH meneken akta pendirian PT Pikiran Rakyat. Buat pertama kalinya, perseroan tadi diumumkan dalam Lembaran Negara No. 58 pada 20 Juli 1973, dan kurang sebulan kemudian PR mendapatkan surat izin terbit dari Departemen Penerangan.
Setahun kemudian, PR melengkapi kemujurannya segera setelah Bank RakyatIndonesia mengucurkan bantuan kredit untuk membeli mesin offset lewat fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PT Dharma Niaga mengapalkan mesin itu dari Inggris pada 1975.
Pemasangan dua bulan. Tepat 12 Mei 1975, PR memulai edisi komersial, dengan tebal delapan halaman. Oplah harian langsung digenjot ke angka 20 ribu eksemplar, kemudian 25 ribu, dan stabil pada angka 35 ribu. Iklan pun mengalami pertumbuhan seiring perkembangan tiras.
Dalam dua tahun pertama edisi komersial, PR terus-menerus mencetak untung, yang memungkinkan dirinya dapat memesan kembali mesin cetak. Mereka lantas membeli dua unit mesin cetak sekaligus. Tahun 1978, mesin-mesin baru mulai bergemuruh. Setiap hari, sekitar 50 ribu eksemplar PR dipompa keluar dan mendominasi pasar media kota Bandung, dan kota-kota lainnya di Jawa Barat. Dan pada Maret 1979, PR hadir dengan edisi mingguannya.
Sebentar kemudian, PR sudah mulai memasang kuda-kuda untuk masuk ke dalam zona perang media nasional, meninggalkan pesaing-pesaingnya diBandung. Kantor-kantor perwakilan segera didirikan. Tidak hanya di Jawa Barat, juga di wilayah lain, termasuk di luar Pulau Jawa. Bersamaan dengan ini, PR membangun jaringan distribusi yang luas dan panjang, mencakup hampir seluruh ibukota provinsi di Indonesia. Untuk mengatasi kemacetan antardaerah, pengiriman paket-paket koran dilakukan melalui pesawat terbang.
Wajah PR benar-benar berubah. Berita-berita nasional dibuat sesemarak mungkin. Demikian pula berita-berita daerah dari luar Jawa Barat. Perhatian terhadap berita-berita setempat, di mana PR berpijak, berkurang.
“Dahulu, bahkan sampai sekarang, ada rasa rendah diri sebagai orang daerah dan segala sesuatu yang berlabel daerah,” tulis Atang Ruswita dalam kertas kerjanya, Repositioning Penerbitan Pers, tempo hari.
“Orang baru dianggap keren kalau sudah ke pusat (Jakarta) atau punya citra nasional.”
BAGAI tim sepakbola yang baru promosi dari divisi satu, PR langsung merasakan kerasnya persaingan divisi utama. Malangnya ia tak punya akar historis yang memberinya kemampuan untuk bertanding di aras nasional. Kompetisi itu benar-benar menguras energinya.
“Dampak dari positioning ini ternyata berat sekali. Pembukaan perwakilan tentu saja menambah beban biaya yang tak kecil. Mengedarkan koran hampir ke seluruh ibukota provinsi juga mahal. Setelah dihitung dengan cermat, maka semua kegiatan di luar Jawa Barat, kecuali Jakarta, merugikan,” kata Atang Ruswita.
Ruswita memberi contoh kasus peliknya mengurus bisnis antarpulau. Misalkan saat PR memiliki piutang agen di salah satu kota di Kalimantan. Tak ada alternatif lain selain segera menutup perwakilannya itu, setelah surat-surat penagihan yang dikirimkan kantor pusat nyata-nyata tak membuahkan hasil.
Tindakan masuk akal. Pasalnya, kalau pun si agen membayar, ongkos penagihan pastilah akan lebih besar dari piutang itu. Lebih celaka lagi, jika debt collector coba-coba dikirimkan ke sana, dan si agen tetap membandel, PR jelas akan rugi dua kali. “Bahkan ongkos kirim dengan pesawat terbang tiap hari ternyata lebih besar daripada uang yang diperoleh dari hasil penjualannya.”
Di bawah ambisi besarnya untuk jadi pemain nasional, belakangan disadari telah membahayakan hidupnya. PR tak lagi punya karakter yang jelas. Jadi koran nasional tidak, jadi koran daerah tidak. Ruswita bilang, kalau orang mau membeli koran nasional, ia kemungkinan besar memilih koran Jakarta. Ketika orang memerlukan koran daerah, ia mungkin memilih koran Bandung lainnya karena kandungan berita daerah PR sedikit.
Pada 1982, PR akhirnya pulang kandang, kembali jadi pemain lokal. Keuntungan yang segera dirasakan dari reposisi ini, paling tidak dapat menghemat biaya sirkulasi dan overhead lain. Keuntungan lain, kembalinya kesetiaan masyarakat Jawa Barat pada PR. Bahkan, kata Ruswita, kesetiaan pembaca PR saat ini sudah menjurus ke fanatisme.
Ia menuturkan sebuah cerita tentang bagaimana para pedagang etnis Cina sampai mempercayai bahwa dagangnya akan seret sekiranya tak melanggan PR. “Jika ada salah seorang anggota keluarga masyarakat Cina di Bandungmeninggal dunia, maka belum bisa dianggap meninggal dunia kalau tidak memasang iklan dukacita di PR.”
Bukan hanya iklan orang meninggal, iklan-iklan lokal lainnya ikut memperteguh fondasi bisnis PR. Kekuatan iklan lokal PR terletak pada iklan mini atau baris. Tak satu pun koran setempat sanggup menandinginya. Bahkan koran-koranJakarta sekali pun. “Iklan mini turut berperan mengangkat derajat media menjadi leader market,” ungkap Syafik Umar, bekas manajer iklan PR, yang kini jadi pemimpin perusahaan di situ.
Dalam salah satu makalahnya, Mengembangkan Iklan Mini, Umar menunjukkan bagaimana kontribusi iklan produk lokal PR, sejak awal 1990, berhasil menyalip kontribusi yang diberikan iklan produk nasional. “Sebelumnya perolehan iklan lokal termasuk iklan mini masih di bawah iklan produk nasional.”
Setelah mengalami fluktuasi, sejak 1990, gross income iklan mini PR sudah mencapai angka Rp 5 miliar dan membesar secara signifikan sejak 1993 hingga Rp 8 miliar lebih. Pada 1996, gross income iklan tersebut hampir mencapai dua kali lipat dari tiga tahun sebelumnya.
“Iklan mini pada awalnya dianggap sebagai iklan yang tidak bermartabat bahkan dilecehkan. Yang dikejar terus-menerus biasanya adalah iklan display atau iklan umum,” kata Syafik Umar. “Tapi iklan mini lebih sering berada di dekat kita dan mendekati kita.”
PR pada akhirnya mampu memosisikan dirinya sebagai salah satu koran papan atas di sektor periklanannya. Membuka halaman demi halaman PR, ibaratnya seperti menyimak lembaran yellow pages. Muhammad Ridlo ‘Eisy sempat menamsilkan medianya sebagai pasar, alih-alih sekadar suratkabar. “Yang dimaksud dengan pasar di sini adalah pertemuan antara penjual dengan pembeli. Penjual diwakili pemasang iklan, pembeli diwakili pembaca.”
Sebagai pasar, PR di mata ‘Eisy lebih komplet daripada pusat perbelanjaan mana pun di Bandung. “Ada barang baru, ada barang bekas. Ada yang menawarkan anjing, kucing, burung, sampai dengan real estate di Australia.”
Orang mau memasang iklan di PR, tuturnya seperti berpromosi, ini lantaran rendahnya angka CPM (cost per mille). CPM adalah hitungan ongkos yang dikeluarkan pengiklan untuk mencapai seribu kepala. Sejak pertengahan 1990-an, angka CPM PR—sebagaimana disampaikan Leo S. Batubara dari Serikat Penerbit Pers beberapa waktu silam—adalah sekitar 11,65. Dengan angka sebesar ini, PR praktis berada di urutan ketiga setelah Pos Kota (3,99) dan Kompas (6,42). Di bawah PR, ada Republika, diikuti Jawa Pos, kemudian Suara Pembaruan, Media Indonesia, dan seterusnya.
Di masa sekarang, setelah pasar media terformat besar-besaran oleh krisis ekonomi, angka CPM mengalami perubahan-perubahan dramatis. Namun, CPM PR agaknya masih tetap rendah. Tertarik menghitung? Misalnya, berapa angka CPM yang Anda dapat untuk mengiklankan telepon genggam yang mau Anda jual dengan memasang iklan dua baris di PR? Dengan harga Rp 15 ribu per baris, Anda membayar Rp 30 ribu. Efektivitas pesan yang didapat, dengan asumsi oplah keseluruhan PR dibaca sedikitnya 700 ribu orang, adalah 30.000 x 1000 : 700.000 = 42,9. Artinya, untuk memberitahu seorang pembaca Anda cukup mengeluarkan Rp 0,043.
BELANJA media Jawa Barat berada di urutan kedua setelah Jakarta. Laporan Asian Newspaper Focus edisi Agustus 2001 mengungkapkan, dari Rp 55,5 miliar rupiah belanja media nasional bulanan, rata-rata sekitar Rp 12,5 miliar terserap Jawa Barat. Jakarta sendiri mengambil sekitar Rp 16,2 miliar.
Jumlah yang ditangguk Jawa Barat hampir dua kali lipat potensi Jawa Timur atau Jawa Tengah yang berada di urutan berikutnya, masing-masing Rp 6,5 miliar dan Rp 6,0 miliar per bulan. Dalam peringkat lima besar ini, Sumatra Utara menyerap sekitar Rp 2,4 miliar.
Jantung perekonomian Jawa Barat terletak di Bandung. Maka, kalau berniat hendak menginvasi Jawa Barat, Anda tak perlu mengecerkan koran ke seluruh pelosok provinsi.
Dari waktu ke waktu, tak terkecuali masa krisis ekonomi, Bandungmemperlihatkan tingkat pertumbuhan yang stabil. Pada 2001 laju pertumbuhan ekonomi naik 7,37 persen dari tahun sebelumnya yang 5,41 persen. Pertumbuhan sebesar ini memacu pendapatan per kapita dari Rp 5,5 juta pada 2000 menjadi Rp 6,6 juta pada 2001.
Bukan itu saja jika Bandung dijadikan titik bidik pengusaha. Hal lain, seperti psikografis pembaca, juga jadi pertimbangan. Bandung dianggap menyimpan potensi kaum muda, yang buat media mana pun di dunia, selalu ditempatkan sebagai pasar masa depan. Potensi ini melekat secara inheren pada statusBandung selaku kota pendidikan terpenting, yang memiliki jumlah universitas negeri terbanyak di Indonesia.
Bagi PR, Bandung adalah lapisan benteng terdalamnya, tempat nyawa diletakkan, tempat hidup dipertaruhkan. Tahun 2001, ketika PR beroplah sekitar 180 ribuan eksemplar, sekitar 110 ribu eksemplar di antaranya dicangkokkan ke Bandung. Paket oplah terbesar kedua, sebanyak 16,1 ribu eksemplar, disebar ke wilayah cincin kota, yakni kabupaten Bandung. Baru sisanya, sekitar 50 ribu eksemplar, disebar ke cincin terluar mulai kota Garut, Sumedang, Cianjur, Purwakarta, dan sejumlah daerah lain di Jawa Barat. Wilayah lain di luar Jawa Barat—yang meliputi Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, serta daerah lain di luar Jawa—hanya kebagian sekitar lima persen dari total oplah, atau sekitar sembilan ribuan eksemplar.
Bisa dipahami jika PR begitu mati-matian mempertahankan pasar Bandung. Sering saya mendengar, agen-agen koran di Pasar Cikapundung—bursa suratkabar terbesar di Bandung, sekaligus Jawa Barat—belum bangun dari tempat duduknya untuk melayani para loper atau pembeli kalau PR dan Kompas belum tiba di sana. “Heselah. Koran lain bisa didiukan ku agen mun PR atawa Kompas can datang. (Susahlah. Koran lain bisa diduduki oleh agen kalau PR atau Kompas belum tiba),” kata Dadi Wiriadinata, bekas kepala sirkulasi Bandung Pos, beberapa waktu lalu.
Keinginan PR untuk berdaulat sepenuhnya bukan cerita kemarin sore. Bekas cakar-cakarnya bisa ditelusuri paling tidak ke awal 1990-an, ketika industri persIndonesia mengalami booming investasi. Di masa itu, koran-koran bertarung keras. Pertumbuhan televisi swasta, kian memasyarakatnya infrastruktur videotext, serta berkembangnya embrio teknologi internet, ikut memberi kecemasan bahwa seolah-olah mereka sedang berada “di akhir zaman.” Perang, karenanya, harus dimenangkan agar bisa melanjutkan hidup.
Dalam situasi itu, perang tidak hanya melibatkan satuan-satuan organis seperti Suara Pembaruan versus Republika versus Kompas atau The Jakarta Post melawan Indonesia Observer, melainkan pula melibatkan jaringan media seperti Kelompok Kompas Gramedia versus Grup Pos Kota versus Grup Surya Pesindo versus Kelompok Jawa Pos.
PR masih bisa bersyukur karena Kelompok Jawa Pos memilih membuka ladang pertempuran di kawasan Indonesia bagian timur. Tapi, dua raksasa lain membuat skenario untuk menyerbu Bandung. Maka, sebelum Kelompok Kompas Gramedia menjalin aliansi dengan Mandala dan Surya Pesindo menggandeng Gala, Grup Pikiran Rakyat mencuri start dengan merangkul Bandung Pos. Miliaran rupiah disuntikkan ke sana, dan Bandung Pos disulap jadi tabloid harian pertama di Indonesia. Mungkin pula di Asia Tenggara.
Harian Mandala dan Gala, pada 1991, dikabarkan mampu menjangkau oplah masing-masing 30 dan 40 ribu eksemplar. Tapi, Bandung Pos melesat jauh 65 ribu eksemplar, yang sekaligus jadi tiras tertinggi dalam sejarahnya. “PR ketakutan sendiri akhirnya,” Dadi Wiriadina berkata suatu ketika. Ketakutan ini diwujudkan Grup Pikiran Rakyat dengan minta agar sebagian oplah Bandung Pos dilarikan ke Jakarta. Dimulai dengan belasan ribu eksemplar, Bandung Pos akhirnya mampu memasok bursa koran Pasar Senen, Jakarta, hampir mencapai 30 ribu eksemplar. Konsumen kebanyakan perantau Sunda.
Kerjasama dengan Bandung Pos berakhir begitu aliansi yang digalang dua raksasa industri pers nasional itu berantakan di tengah jalan. Dan PR kembali mengendalikan pasar media kota Bandung.
Gangguan atas pasar kota Bandung tampaknya lagi-lagi berkembang menyusul dipermudahnya pembikinan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) segera sesudah kekuasaan rezim Soeharto tamat. Apa yang dilakukan PR ketika mendengar Kelompok Kompas Gramedia bakal membuat koran baru? PR kembali merogoh koceknya dalam-dalam untuk mengambil-alih Gala. Berhasil. Galamedia pun meluncur ke jalanan, sebelum Kelompok Kompas Gramedia menerbitkan Metro Bandung.
Apa boleh buat, ketakutan akan datangnya pesaing serius telah menguras energi Grup Pikiran Rakyat. Akibatnya, bukan saja oplah PR menurun, yang diikuti kemerosotan margin keuntungan, sang induk pun tak punya kemampuan memadai untuk memberikan gizi terhadap anak-anaknya, sehingga pertumbuhan mereka jadi lamban. Hikmah, tabloid mingguan yang memusatkan perhatian pada isu-isu agama Islam, malahan masuk liang lahat pada 2001. Sebelumnya, Suara Rakyat Semesta, tabloid mingguan terbitan Palembang, juga tersungkur untuk tak bangun lagi.
MARET 2002, di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Tetes-tetes embun di markas PR baru saja mengering. Pagi itu, tak seperti biasanya, lapangan parkir sudah dipenuhi beragam kendaraan roda empat. Namun, di ruangan redaksi, situasi datar-datar saja. Tak ada yang spesial. Jumlah awak redaksi yang hadir pun dapat dihitung dengan jari. Selebihnya, cuma petak-petak partisi tak berpenghuni.
Pusat kesibukan ternyata berlangsung di sayap kanan areal perkantoran. Parapenggede PR terlihat mendominasi ruangan. Mereka sedang mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun anggaran 2001-2002. Paras mereka tidak seceria tahun-tahun sebelumnya. Bisnis sedang lesu.
Ekonomi Indonesia memang sedang sakit dalam lima tahun terakhir, mengiringi jatuhnya nilai rupiah. PR masih beruntung bisa bertahan dan menangguk laba, meski tidak sebesar dulu-dulu.
“Kecil. Rata-rata 400 juta sebulan,” kata Nina Hilman, salah seorang pemilik saham, mengacu jumlah keuntungan Rp 400 juta.
Bukan perolehan terbaik. Angka sebesar itu hanya sepertiga gross income iklan baris PR pada 1996 yang mencapai sekitar Rp 15 miliar.
Orang luar boleh tidak percaya. Karyawan boleh ragu. Bahwa petinggi PR telah menyembelih margin keuntungan sejadi-jadinya, boleh pula jadi isu. Tapi, mungkin benar adanya, PR hari ini tidak segesit kemarin. Indikator kelesuan bisa dilacak ke jumlah oplah yang terus menurun. Sebelum krisis ekonomi, katakanlah pada 1996, tiras harian PR mencapai 250 ribu-300 ribu eksemplar. Per Mei 2002, tiras tinggal sekitar 110-120 ribu eksemplar.
Secara bisnis, oplah sebesar itu belum bisa dibilang menguntungkan. Setiap bulan—menurut perkiraan Kartono Sarkim, sekretaris direksi Grup Pikiran Rakyat—seorang pelanggan harus disubsidi sekitar Rp 7 ribu-Rp 10 ribu per eksemplarnya. Artinya, harga langganan ideal PR jatuhnya sekitar Rp 45-50 ribu per bulan, bukan seperti sekarang yang sebesar Rp 39 ribu.
Dihadapkan dengan kondisi tersebut, PR praktis bergantung sepenuhnya pada pemasukan iklan, yang untuk kategori hitam-putih saja per halamannya bisa mencapai nilai jual bruto senilai Rp 40 juta. Setiap hari, enam sampai 10 halaman habis dikavling para pengiklan. Toh sebesar apapun pendapatannya, margin keuntungan yang diperoleh tidak sepenuhnya berbuah deviden dalamlima tahun terakhir ini. Apa pasal? PR masih harus menyubsidi anak-anak perusahaannya.
Saya mencatat, setelah Hikmah dan Suara Rakyat Semesta hancur-lebur, Grup Pikiran Rakyat masih memiliki Mitra Bisnis (Bandung), Priangan (Tasikmalaya), Pakuan (Bogor), Galura (Bandung), Galamedia (Bandung), Fajar Banten (Serang), Mitra Dialog (Cirebon), radio Mustika FM 107,55 Mhz, percetakan dan penerbit buku Granesia, serta sejumlah warung telekomunikasi yang tersebar di berbagai daerah, mulai Jakarta sampai Surabaya. Kecuali warung telekomunikasi, hampir seluruh anak perusahaan Grup Pikiran Rakyat dikabarkan berjalan terseok-seok. Jangankan mendapat keuntungan, menyentuh titik impas saja kemungkinan masih jadi teka-teki besar. Praktis, kehidupan mereka disangga sepenuhnya oleh PR.
Gambaran tergopoh-gopohnya bisnis anak-anak perusahaan PR paling tidak bisa disimak pada Mustika FM, yang belakangan disewakan kepada Dudi Nandang, seorang pengusaha restoran. Di pihak lain, Galura, tabloid umum mingguan berbahasa Sunda, hanya mampu beredar dalam jumlah oplah sekitar empat ribu eksemplar per edisi. Iklan yang diserap pun masih bisa dihitung tanpa harus menggunakan kalkulator. Jumlah tiras sebesar itu, juga jadi bagian hidup Pakuan, suratkabar yang terbit dua kali dalam seminggu, dengan ketebalan delapan halaman setiap terbit.
Di antara tabloid yang dimiliki grup ini, barangkali oplah Mitra Bisnis masih agak lumayan, walau tidak sebesar sebagaimana tertulis dalam berkas-berkas promosinya. Mitra Bisnis, mula-mula bernama Mitra Desa, beredar seminggu sekali dengan oplah tujuh ribu eksemplar. Dalam berkas resmi buat publik, Mitra Bisnis ditulis beroplah sebesar 40 ribu eksemplar.
Oplah terbesar di antara anak perusahaan adalah Galamedia. Koran harian yang memusatkan perhatian pada pemberitaan kriminal ini diambil-alih dari tangan pengusaha media Syamsuar Adnan tahun 1999. Order cetak Mei 2002 menunjukkan, Galamedia dicetak 30 ribu eksemplar per hari, atau lebih kecil 20 ribu eksemplar dari publikasi resmi. Angka sebesar ini buat sebagian karyawan sebenarnya masih kelewat besar. Oplah sebenarnya paling banter mencapai 16-17 ribu eksemplar per terbit.
Dengan oplah tersebut dan minimnya iklan yang masuk, bisa dipahami kalau Galamedia belum bisa meraih keuntungan, sekurang-kurangnya mencetak angka pulang pokok. Betapa pun, modal yang diinjeksikan ke dalamnya bukan jumlah kecil. Selama tahun pertama saja, sedikitnya Rp 4 miliar dialirkan ke sana untuk pelbagai pos pengeluaran, mulai investasi peralatan kerja, pembaruan struktur penggajian, jaringan distribusi sampai promosi gila-gilaan. Pada bulan-bulan promosi, Galamedia dijual Rp 500 per eksemplar. Sejumlah tenaga sales promotion girls diterjunkan ke sejumlah titik perniagaan di Bandung.
“PR mah gengsi-gengsian wungkullah. Nyieun itu, nyieun ieu. Hutang we salaput hulu (PR cuma gengsi-gengsian. Bikin itu, bikin ini. Utang akhirnya melebihi kepala),” begitu Suyatna Anirun, bekas redaktur kebudayaan PR, mengomentari pola ekspansi Grup Pikiran Rakyat. “Salaput hulu” atau “melebihi kepala” yang dimaksud mendiang adalah ungkapan orang Sunda yang bisa ditafsirkan “melebihi kemampuan untuk membayar” – bahkan dengan menyiagakan seluruh aset sekalipun.
JAKARTA, Oktober 1997. Sesaat sebelum krisis finansial menerkam Indonesia, saya mengikuti workshop manajemen pers yang digelar Serikat Penerbit Suratkabar bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Yang disebut terakhir, pada masa itu, merupakan institusi terdepan di Indonesia, yang ikut menempa manajer-manajer andal.
Lewat event ini, buat pertama kalinya saya bertemu dengan para pengambil keputusan dari pelbagai media di tanah air yang jadi peserta kegiatan. Mereka, kalau bukan redaktur, pastilah manajer bisnis. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi, kami mempelajari banyak hal. Dari kebijakan pemberitaan sampai membuat tajuk rencana, dari membangun visi dan misi perusahaan sampai pemetaan industri pers di Indonesia, dari task force sampai menghitung bunga bank dan depresiasi. Sebulan penuh kami belajar dari pagi hingga malam. Bahkan, bila ada tugas, tengah malam kami masih memelototi layar komputer.
Sekali waktu, saya mendengar Suherlan, keponakan Atang Ruswita, bernyanyi-nyanyi kecil, ”Cita-citaku ingin jadi wapemred….”
“Kenapa tidak jadi pemred saja sekalian?” saya larut dalam keceriaannya.
“Ho… hohooo.”
Suherlan, saat itu datang sebagai redaktur pelaksana Mitra Dialog, salah satu koran mantel Grup Pikiran Rakyat untuk karesidenan Cirebon. Mitra mulanya bernama PR Edisi Cirebon, terbit seminggu sekali.
Referensi saya tentang Grup Pikiran Rakyat bertambah lagi hari itu. Di lingkungan Grup Pikiran Rakyat, jabatan pemred (pemimpin redaksi) hanya buat seorang: Atang Ruswita. Jabatan tertinggi di sektor redaksi, baik di PR maupun anak-anak perusahaannya, tinggal wakil pemimpin redaksi. Ditilik dari sini, Yoyo Siswaya Adiredja beruntung. Begitu Grup Pikiran Rakyat membeli Galamedia, ia langsung jadi pemimpin redaksi. Isu pun bertiup kencang, Adiredja disebut-sebut kandidat putra mahkota. Lebih-lebih tatkala dirinya diangkat juga sebagai pemimpin harian redaksi PR bersama A.M Ruslan dan Widodo Asmowiyoto. Triumvirat inilah yang sehari-hari bertanggungjawab atas kebijakan redaksi koran pagi itu.
“Bapak sudah tua, dan umur siapa tahu, besok atau lusa mungkin meninggal. Siapa orang paling tepat untuk memimpin PR nanti?” saya bertanya pada Soeharmono Tjitrosoewarno, tokoh pendiri yang kini jadi ketua Dewan Komisaris Grup Pikiran Rakyat.
“Saham kan bisa diwariskan. Ya, tergantung siapa yang akan dipilih rapat pemegang saham,” katanya di seberang telepon Mei lalu.
“AM Ruslan bagaimana?”
“Kalau dipilih, kenapa tidak?”
“Yoyo atau Suherlan?”
“Saya tidak punya komentar. Saya tidak mau bicara person-person. Omongan saya bisa jadi rujukan nanti.”
Grup Pikiran Rakyat dikenal sebagai perusahaan tertutup. Birokrasinya tak ubahnya unit-unit instansi-instansi pemerintahan. Seseorang yang hendak berhubungan dengan grup tersebut, misalnya, harus melewati meja bagian hubungan masyarakat dan protokoler. Jarang perusahaan-perusahaan swasta lain di Indonesia punya bagian ini.
Ketertutupan kelompok usaha tersebut tidak hanya buat publik luas. Karyawan sendiri banyak yang tidak mengetahui siapa persisnya majikan mereka, pemegang saham Grup Pikiran Rakyat itu. Ini juga berlaku untuk jenjang karir. Pendeknya, seorang yang hari ini asisten redaktur, belum tentu besok jadi redaktur. Dan mereka yang hari ini redaktur, belum jadi jaminan lusa bakal jadi redaktur pelaksana atau wakil pemimpin redaksi. Bisa-bisa mereka ditendang ke tempat lain, taruhlah ke anak perusahaan yang masih gelap nasib hari depannya.
Lihat saja Enton Supriatna, eks asisten redaktur kota PR. Segera setelah terlibat kasus gugatan Azmi Thalib Chaniago terhadap PR, Supriatna dikirim ke Serang untuk mengelola Fajar Banten. Chaniago, pemimpin redaksi tabloid Pasopati, menggugat karena dirinya merasa terpukul oleh pemberitaan “Tutang Akan Adukan Wartawan Pasopati” yang dimuat PR 18 Agustus 2001. Berita itu, menurut Chaniago, “tidak memenuhi standar penulisan sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan.”
Supriatna terbilang beruntung lantaran masih bisa bergiat di lapangan jurnalistik. Di luar dia, banyak karyawan yang dilempar ke jurusan lain, yang kadang-kadang tak ada hubungannya dengan perjalanan karir yang selama ini ditempuhnya.
Saya punya banyak catatan. Husni Agus, salah seorang wartawan yang dianggap kritis dan punya integritas profesional, sejak awal 1990-an, dikenal sebagai editor desk internasional. Kini, ia mengurusi percetakan. Nasib Agus sebangun dengan Usep Romli, bekas redaktur pelaksana Hikmah, yang juga terbuang ke percetakan. Belum lagi Wan Abbas yang bertahun-tahun mendalami liputan hiburan, terutama musik, belakangan ditaruh di divisi periklanan setelah meninggalkan kursi editor PR Minggu. Sebelumnya, Marzuki Salim, editor desk olahraga PR, terjerembab ke koperasi karyawan Grup Pikiran Rakyat.
Yang lebih pahit, tidak sedikit. Baedarus, redaktur pelaksana PR yang membawahi pemberitaan kota, karirnya berhenti dan akhirnya … non-job. Hal senada juga dialami Dadang Bainur, redaktur pelaksana PR yang membawahi desk opini dan sejumlah suplemen.
Kalau daftar hendak diperpanjang, ada Muhammad Ridlo ‘Eisy, seseorang yang disebut-sebut “otak PR.” Ia jarang ngantor setelah meninggalkan jabatannya sebagai manajer Badan Pengembangan dan Penelitian Grup Pikiran Rakyat. ‘Eisy bukan orang sembarangan buat lingkungan Grup Pikiran Rakyat. Bekas wakil redaktur pelaksana PR ini, setelah mengeyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung, sempat mengikuti program Master of Business Administration yang diselenggarakan Yayasan Telkom dan Asian Institute of Management Manila. Di sana ia jadi mahasiswa terbaik.
SAHAM Grup Pikiran Rakyat berjumlah sekitar 700 lembar, dalam dua seri. Sekitar 300 lembar seri A, sisanya seri B. Anggaran dasar 1995 menyebutkan, saham seri A dihargai Rp 2 juta per lembar. Sedangkan seri B setengahnya. Sejak Maret sampai Juni 2002, mereka masih bergelut dengan serangkaian rapat umum pemegang saham yang diikuti kerja para petugas audit, sehingga belum lagi bisa dibuat anggaran dasar perusahaan yang baru.
Berdasar anggaran yang ada, mayoritas saham dikuasai pendiri. Asal tahu saja, PR—yang menghidupi sepenuhnya Grup Pikiran Rakyat—didirikan sedikitnya oleh 33 orang. Tak ada yang dominan di situ. Seluruh pendiri masing-masing menguasai 10 lembar saham seri A dan 10 lembar saham seri B. Sisa saham seri B diberikan kepada mereka yang dianggap berjasa mengembangkan PR. Jumlah buat mereka tidak banyak. Hanya satu sampai lima lembar. “Pak Jakob kaget mendengar ini,” kata Kartono Sarkim, mengacu Jakob Oetama, godfather Kelompok Kompas Gramedia.
Dari 33 pendiri itu, sebagian di antaranya sudah melepaskan kepemilikannya, dengan cara dijual. Mereka katakanlah Moch. Moekrim, Soewardi, Soenarsono, Soekarna, atau Soeradi S.W. Sedangkan mereka yang meninggal dunia, mewariskannya kepada istrinya, selain anaknya. Dapat disebut di sini Bram M. Darmaprawira yang mewariskan kepada Dewi Hartati, Warsono Tidara kepada Toto Rusmini, Parman Djajadiredja kepada Titi Gartiah, atau S.O. Manusama kepada Euis Ellis Suparman.
Memiliki saham di PR bukan saja dapat dividen tiap akhir tahun. Mereka pun, dimungkinkan dapat memasukkan sanak-familinya untuk bekerja di sana.
Struktur manajemen agaknya memberi jalan masuk untuk itu. PR bukan lagi sekadar sebuah koran, tapi juga pada gilirannya jadi sebuah label untuk sebuah konglomerat media, yang untuk Jawa Barat tiada bandingannya. Dalam perubahan ini, format manajemen celakanya tidak ikut berubah. Ia, sejauh ini, masih tetap menganut model manajemen keluarga. Dalam model ini, pola pengambilan keputusan biasanya lebih didasarkan pada “naluri kekeluargaan” (management by exception) ketimbang management by objectives.
Salah satu ekses yang kemudian muncul dan berkembang adalah menguatnya peran patron-client keluarga, atau dalam bahasa gamblangnya nepotisme. Siapa pun yang mengamati perilaku organisasi PR, tahu kalau sebagian karyawan di situ terdiri atas anak-anak dan saudara para pemegang saham. Mereka bahkan menempati posisi-posisi kunci.
Saya mencatat, Atang Ruswita menempatkan setidaknya tiga anaknya. Suherlan jadi editor kota. Januar Primadi menempati posisi manajer puncak divisi periklanan. Meida Dwiyani, bekas manajer periklanan tabloid Hikmah, kini juga berada di sana.
Anak-anak pendiri lainnya, bisa disebut Rayendra Alamsyah serta Perdana Alamsyah, putra Sakti Alamsyah. Mereka masing-masing editor luar negeri PR serta komisaris Grup Pikiran Rakyat. Ada juga Kartono Sarkim, putra Sarkim, yang juga pendiri PR, sebagai sekretaris direksi Grup Pikiran Rakyat.
Kalau mau ditambah, bisa disebut Nina Hilman. Bekas reporter kesehatan ini, yang biasa meliput dengan Mercedes Benz serial terbaru, kini menduduki jabatan strategis sebagai kepala bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Grup Pikiran Rakyat. Seluruh persentuhan dunia luar harus melewati mejanya.
Perempuan wangi ini pewaris saham almarhum Achmad Sarbini.suarakaltim.com* Agus Sopian,Mon, 1 July 2002/pantau.or.id. foto :